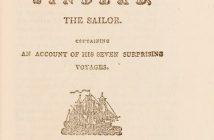Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (Jaranan)
SEBAGAIMANA anak lainnya di Jawa yang senang dolanan, demikian juga dengan dirinya. Berayahkan seorang kerabat dekat Keraton Paku Alam, membuat dirinya tumbuh di tengah lingkungan keraton sekaligus mereguk segenap kosmologi keraton. Tetapi dirinya sendiri terlatih hidup dalam kesahajaan, jauh dari keangkuhan.
Di masa kecilnya itu ia pun begitu akrab dengan dunia wayang. Ia menyukai tokoh-tokoh ksatria pemberani dalam dunia wayang, dan menyerap segenap nilai-nilai kebaikan darinya. Di antara tokoh wayang paling dikagumi dan diproyeksikan sebagai ideal bagi dirinya adalah Yudhistira dan Kresna. Bahkan, kabarnya, di usia 12 tahun ia telah menuangkan dalam bait-bait sajaknya yang berisikan pujaan tentang Yudhistira.
Baginya, Yudhistira perwujudan ideal raja yang baik, yang di dalam jaringan pembuluh darah tubuhnya dialiri darah putih, perlambang keistimewaan sekaligus kesucian dirinya. Dalam situasi apapun, Yudhistira tak pernah marah, membantah, maupun menolak segala permintaan orang. Yudhistiralah sang penjaga kitab suci Kalimasada, yang mencatat segenap rahasia agama dan semesta, sebagai sumber kekuatannya.
Sementara Kresna, sang inkarnasi Dewa Wisnu yang juga sepupu para Pandawa itu merupakan politikus super cerdas, diplomat ulung sekaligus ahli strategi perang terhebat. Kresnalah sesungguhnya tokoh vital dibalik kemenangan Pandawa melawan Kurawa dalam Bharatayudha.
Hidup dan tumbuh di lingkungan Keraton Paku Alam, baginya merupakan nasib dan nasab yang sungguh harus disyukurinya. Sebab hal itu menandai keberlimpahan berkah yang teramat besar dari Sang Maha Pencipta pada dirinya. Sehingga di masa politik etis pemerintahan kolonial Belanda itu, ia berkesempatan bersekolah di ELS, Sekolah Dasar yang diselenggarakan pemerintah kolonial, ketika justru banyak anak-anak boemipoetra lain seusianya tak diperkenankan sekolah saat itu.
Lewat kehidupan di lingkungan istana pula di masa kecilnya, ia berkesempatan mengakses buku-buku koleksi pamannya yang seorang raja, khususnya buku-buku bertema perjuangan. Meski awalnya ketika ia membaca buku-buku koleksi keraton itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lantaran ia takut dimaraahi sang raja.
Suatu hari, kabarnya, ia kepergok sang raja ketika mengendap-endap hendak mengembalikan buku yang dipinjamnya diam-diam ke lemari perpustakaan Keraton. Namun raja yang sebenarnya telah lama tahu ulah keponakan kecilnya itu, bukan malah memarahinya, melainkan justru memuji semangatnya membaca. Bahkan menghadiahinya buku-buku bertema perjuangan kepadanya. Tentu itu membuatnya semakin bergairah membaca dan belajar.
Meski ia keponakan raja, tapi ayahnya sendiri sebenarnya tak terlalu bagus ekonominya saat itu. Tapi ia toh akhirnya berkesempatan juga melanjutkan sekolah elit kalangan priyayi, STOVIA, sebuah sekolah dokter boemipoetra di Batavia pada tahun 1905.
Di STOVIA, selain terus menunjukkan kinerjanya sebagai seorang pembelajar sejati, ia menjalin hubungan dengan kalangan nasionalis boemipoetra di masa-masa paling awal kemunculan dan perluasan embrio gerakan kebangsaan di negerinya. Benih-benih jiwa ksatria yang telah dipupuknya sejak kecil terus membesar lewat minatnya dan upaya pada usaha-usaha perjuangan menuju kemerdekaan bangsanya dari belenggu penjajahan.
Di usia muda, sekitar 18 tahun, di tahun 1907 ia memutuskan untuk menikahi gadis pujaan hatinya, Soetartina Sasraningrat. Lalu ia ikut dalam mendirikan perkumpulan Boedi Oetomo pada tahun 1908, dan ditunjuk menjadi sekretaris pertama.
Di Boedi Oetomo ia cuma aktif selama setahun. Agaknya hal itu mirip dengan keterlibatan Tjipto Mangoen Kosoemo, dokter Jawa koleganya, yang cuma aktif selama setahun di Boedi Oetomo, sebagai bentuk penolakan atas pengalihan pimpinan kepada anggota-anggota Boedi Oetomo yang lebih tua dari kalangan Bangsawan.
Dua tahun setelah perkawinannya itu, di tengah kesulitan ekonomi yang melilit, dengan berat hati ia meninggalkan sekolahnya di STOVIA. Namun tak sedikit pun cita-cita mulia bagi negeri tercintanya memudar, bahkan terus menyala berkobar-kobar di dalam dadanya.
Berkembang Sebagai Pemuda Radikal
Beberapa jenis pekerjaan kemudian dilakoninya sebagai bagian dari tuntutan hidup. Diantaranya sebagai juru tulis di pabrik gula Ponorogo. Dan tahun 1911, ia sempat bekerja di sebuah pabrik farmasi di Yogyakarta.
Namun di luar itu, naluriya yang telah terasah sejak kecil sebagai ksatria sejati yang mencita-citakan tata kehidupan yang jauh lebih baik bagi negerinya, terus saja dipupuk, diasah dengan baik dan diaktualisasikannya secara nyata.
Sekitar tahun-tahun tersebut, ia mengirim tulisan-tulisannya ke beberapa media massa yang terus tumbuh di pelbagai kota kala itu sebagai salah satu alat perjuangan modern bagi kaum boemipoetra. Di antara tulisannya itu dibuat atas pesanan media bersangkutan.
Ternyata tulisan-tulisannya itu membuat Douwes Dekker– seorang Indo radikal-subversif yang anti Barat, cucu dari saudara Eduard Douwes Dekker (1820-1877) sang penulis “Max Havelar”, dan memiliki pergaulan hangat dengan para pelajar STOVIA–tertarik pada tulisan-tulisannya.
Lalu Dekker pada 1912 memintanya menjadi redaktur surat kabar De Expres di Bandung, yang setahun sebelumnya, pada Maret 1911, telah meluncurkan edisi perdananya. Ia bersedia atas tawaran Dekker tu serta menetap di Bandung.
De Expres sendiri kemudian menjadi organ penerbitan berbahasa Belanda dari partai yang dibentuk dan diinisiasi Dekker pada September 1912, yakni Indische Partij (IP).
Selain menjadi redaktur De Expres, ia pun tentu bergabung dengan IP, meski partai itu sendiri pada perkembangannya kemudian menghilang dari arena pergerakan. Hal itu lantaran IP dua kali ditolak saat hendak memperoleh status pengakuan sebagai badan hukum resmi oleh pemerintah kolonial Belanda.
Seiring itu, ia pun menjadi Ketua Cabang Sarekat Islam (SI) Bandung, yang dipimpin Cokroaminoto dan berpusat di Surabaya. Dalam sebuah Kongres SI tahun 1913, ia mengusulkan agar SI menghapus sarat muslim dalam keanggotaan. Sebab baginya yang terpenting adalah solidaritas Hindia. Dengan bahasa lain ia ingin agar SI diubah menjadi Sarekat Hindia.
Usulan itu menandai sikap oposisi SI cabang Bandung terhadap SI Pusat di bawah Tjokroaminoto. Tapi mengingat di massa itu IS masih berada di bawah atmosfir politik “kesetiaan kepada Negeri Belanda dan pemerintahan Hindia”, tentu saja usulannya pada kongres SI itu dipandang terlalu radikal, dan kongres pun menolaknya begitu saja.
Kemudian pada 8 Juli 1913, De Expres mengumumkan bahwa di Bandung telah resmi dibentuk sebuah Komite bernama “Inlandsch Comite tot Herdenting van Nederlands Honderdjarige Vrijheid” (Komite Bumiputra untuk memperingati Seratus Tahun Kemerdekaan Belanda), atau Komite Boemipoetra. Saat itu Dekker sedang melakukan perjalanan ke Eropa untuk suatu urusan.
Komite Boemipoetra itu sesungguhnya sebuah komite tandingan atas Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda yang dibentuk Pemerintah Belanda, yang bermaksud menggelar perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis, dengan cara menarik uang dari rakyat Indonesia sebagai negeri jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut.
Empat hari kemudian, 12 Juli 1913, lewat pamflet yang dibuat Komite Boemipoetra, ia tercatat sebagai sekretaris komite itu, bersama dengan enam orang anggota lain, yakni Tjipto Mangunkoesoemo (ketua), Soejatiman Soeriokoesoemo (wakil ketua), Wignjadisastera (Bendahara), Nyonya Soeraja, Roem, dan Abdul Muis.
Pamplet itu pun diantaranya menerangkan niat komite untuk mengirimkan telegram ucapan selamat kepada ratu Belanda, Wilhelmina, di perayaan 100 tahun Kemerdekaan Belanda itu.
Juga meminta sang Ratu agar menghapus Pasal 111 Ordonansi Konstitusional (Indische Staatsregeling). Sebab pasal itu dinilai amat kontradiktif, dimana meskipun memberi hak bagi boemipoetra untuk berserikat dan berkumpul, namun demi ketertiban umum, orang boemipoetra harus diawasi dan dibatasi ruang geraknya lewat peraturan. Selain itu sang Ratu pun diminta membentuk Parlemen Hindia.
Lalu pamplet kedua diproduksi dan disebarkan secara luas, dengan jumlah sekitar 5.000 eksemplar. Isinya adalah sebuah tulisan yang telah dipersiapkan olehnya dengan matang dan seksama, berjudul “Als ik eens Nederlander was” (Seandainya saya seorang Belanda).
Selain dalam bahasa Belanda, pamplet itu pun disebar dengan melampirkan terjemahan pamplet itu dalam bahasa Melayu, dengan tujuan agar isinya bisa dibaca oleh rakyat boemipoetra secara lebih luas lagi.
“Sekiranya aku seorang Belanda, Aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh is irlander memberikan sumbangan untuk perayaan itu,” demikian tulisnya dalam Pamplet itu.
Lebih lanjut suara dari pamplet itu terus menyergap dan menohok para pembacanya, khususnnya pembaca Belandanya, lewat kalimat-kalimat trengginasnya:
“Pikiran untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada keperntingannya sedikitpun.”
Artikelnya dalam pamplet itu sesungguhnya merupakan artikel pertama kalangan inlander yang ditulis dalam bahasa Belanda–yang turut melampirkan terjemahan dalam bahasa Melayu–untuk menyatakan sikap dan pandangan secara terbuka tentang pemerintahan kolonial.
Pernyataan politik dalam artikel itu, dari seorang inlander yang menggunakanan bahasa yang sama dengan bahasa yang dipakai pemerintahan yang dikritiknya, lantas dengan cepat dikaitkan paralelisasinya dengan tokoh wayang Bima.
Dalam dunia wayang, Bimalah satu-satunya ksatria yang bisa berbicara memakai bahasa “ngoko” sekalipun saat berbicara dengan para dewa. Bahasa ngoko dalam masyarakat Jawa digunakan pada orang yang sama derajatnya. Atau antara atasan dengan bawahan, dan bukan sebaliknya.
Artikelnya itu mengkonfirmasi kemampuannya yang luar biasa dalam menciptakan dan memainkan bahasa. Dan memang kreasi kata-katanya digunakan sebagai simbol untuk merujuk pada esensi situasi atau suatu perbuatan tertentu.
Dalam hal kepiawaiannya menciptakan simbolisme dan gaya yang bertalian dengan sistim budaya tradisional, yang mana hal demikian sesungguhnya menjadi salah satu sifat dasar dari kepemimpinan kaum nasionalis boemipoetra di masa awal itu, menempatkan dirinya sebagai yang terdepan.
Lewat artikel itu pula yang kemudian meneguhkan kewibawaannya sebagai salah satu pepopor pergerakan menuju kemerdekaan bangsanya, sekaligus menjadi inspirasi bagi perlawanan lebih jauh dan keras kaum nasionalis boemipoetra saat itu dan di masa-masa berikutnya.
Sementara bagi pemerintah kolonial Belanda, artikelnya itu dipandang sebagai ejekan, hasutan dan “serangan keji” yang mengganggu keamanan dan ketertiban (rust en orde) di tanah jajahan. Serangkaian interogasi kemudian dilakukan terhadap para anggota Komite Boemipoetra.
Sampai akhirnya pemerintahan kolonial Belanda, lewat Gubernur Jenderal Idenburg, memutuskan untuk melakukan pengasingan ke negeri Belanda kepada dirinya dan kedua koleganya, yakni Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker.
Ketiganya lalu meninggalkan Pulau Jawa pada 6 September 1913 ke tanah pengasingan. Masa pengasingannya di Eropa, dijalaninya sekitar 6 tahun. Sementara untuk Dekker sekitar 5 tahun, dan Tjipto sekitar setahun.
Pengasingan dan Pasca Pengasingan
Namun di pengasingan, justru ia berkesempatan terus mengembangkan kapasitas dirinya, tak terkecuali tetap mencurahkan perhatian pada cita-cita perjuangan yang sudah digelutinya.
Di pengasingannya itulah kabarnya ia belajar tentang dunia pendidikan. Ia mengapresiasi teori-teori pendidikan Tagore, yang saat dirinya tiba di Eropa tahun 1913, Tagore baru saja memperoleh Hadiah Nobel.
Sempat bergabung dengan dewan sekolah Montessori yang pertama dibuka tahun 1915 di negeri Belanda. Menjalin kerjasama dengan “guru cinta kasih” Jan Lightart. Dan ia pun mempelajari gagasan-gagasan antroposofi Rudolf Steiner (1861-1925).
Bakat jurnalistiknya yang telah ditunjukkan di negerinya, ia lanjutkan dengan mendirikan Persbiro (Kantor Berita) Indonesia di Denhag tahun 1913. Tujuan kantor berita itu untuk menghimpun dan menyebarkan informasi dan berita tentang gerakan nasionalis di Indonesia. Di samping itu untuk memperkenalkan kesenian pertunjukan tradisional kepada orang Belanda dan mempropagandakan kebudayaan negeri asalnya.
Pada Agustus 1916, di Den Haag digelar Kongres Pengajaran Kolonial Pertama (Eerste Koloniaal Orderwijscongres). Di Kongres itu, dirinya diundang menjadi pembicara untuk tema kedua yang mengangkat tentang “Bahasa apa yang harus digunakan di sekolah-sekolah Boemipoetra?”
Melalui Kenji Tsuchiya (1992), kita akhirnya tahu pendapatnya tentang bahasa dalam kongres itu, yang bisa disimpulkan sebagai berikut:
Bahasa dan bangsa adalah satu. Pengingaran terhadap bahasa merupakan menyimpangan dan berbahaya. Dan pembelaan atas penyimpangan itu adalah kejahatan.
Jika dipandang sebuah bahasa umum diperlukan untuk negeri Hindia, maka bahasa itu bukanlah Bahasa Belanda, melainkan Bahasa Melayu yang telah dipakai secara efektif sebagai lingua franca.
Bahasa Belanda perlu sebagai kunci mendapat ilmu dan teknologi (Iptek) Barat, ataupun alat untuk mendidik cendikiawan yang bisa menerjemahkan Iptek itu.
Sepulangnya dari pengasingan, ia sempat, diantaranya, mengajar di sekolah swasta Adhi Dharma milik kakaknya, RM Soerjopranoto. Ia juga terlibat dalam perkumpulan Selasa Kliwon, yang didirikan tahun akhir 1921 yang mengadakan latihan spiritual oleh sembilan orang Jawa.
Selain dirinya, dalam perkumpulan itu terdapat pula Ki Ageng Soerjomentaram, Soetatmo Soeriokoesumo, Pronowididgdo, Prawirowiworo, RM Gondoatmodjo, BRM Soebono, Soerjopoetro, R Soetopo Wonobojo, dan Soerjodirdjo. Sebagian besar anggota perkumpulan itu memiliki pertalian kekerabatan dengan keluarga Paku Alam, dan juga kaitan dengan perkumpulan Boedi Oetomo.
Perkumpulan itu sendiri diketuai oleh Ki Ageng Soerjomentaram, seorang yang lahir sebagai Pangeran Kesultanan Yogyakarta, tapi menolak kedudukan di Istana dengan meninggalkan jabatannya dan hidup sebagai petani. Kisahnya itu mengingatkan pada tokoh Semar dalam pewayangan.
Dalam pertemuan-pertemuan perkumpulan Selasa Kliwon kemudian diambil sebuah keputusan penting terkait dunia pendidikan. Yakni merencanakan penerapan kemudahan pendidikan untuk generasi muda dan kegiatan pendidikan untuk orang dewasa. Rencana pendirian sekolah itu lalu terpublikasi lewat surat kabar De Expres.
Sekolah itu diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa (Lembaga Perguruan Nasional Taman Siswa). Sekolah pertama didirikan pada 3 Juli 1922, yakni dengan membuka kelas taman anak-anak (kindergarten) dan kursus guru.
Saat itu juga, di pendopo depan sekolah Adhi Dharma, ia berpidato mengikhtisarkan tujuh butir tujuan mendirikan Taman Siswa, yang kemudian dikenal sebagai “prinsip-prinsip yag tidak bisa berubah”.
Berikut ketujuh prinsip itu (Ibid):
Pendidikan dan pengajaran pada setiap bangsa bertujuan memelihara bibit yang diturunkan dari generasi lebih dulu sehingga bangsa itu dapat tumbuh secara fisik dan spiritual. Sebagaimana individu harus mengembangkan jiwa dan badannya, demikian pula suatu bangsa harus berusaha mengembangkan kebudayaan dan masyarakatnya. Cara-cara mencapainya harus didasarkan atas adat istiadat bangsa. Dengan cara ini bangsa akan bisa berkembang cepat dan licin sesuai kodrat alam.
Pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat jauh dari kebal terhadap pengaruh-pengaruh politik kolonial. Tapi anehnya pendidikan itu dengan senang hati diterima oleh kaum borjuis (priyayi dan kaum menengah), yang mengirim anaknya ke sekolah-sekolah dimana pendidikan tidak membantu mengembangkan badan dan pikiran, tapi semata-mata memberikan surat diploma yang memungkinkan mereka menjadi buruh.
Pendidikan dalam masyarakat kolonial telah mencegah terciptanya masyarakat sosial, tetapi menghasilkan suatu kehidupan yang tergantung kepada bangsa-bangsa barat. Keadaan ini tidak mungkin diselesaikan semata-mata dengan konfrontasi fisik melalui gerakan politik, tapi memerlukan bibit-bibit gaya hidup yang merdeka, ditanamkan di jiwa rakyat melalui sistim pendidikan nasional.
Harus diadakan sistim pendidikan baru yang menguntungkan masyartakat boemipoetra, bukan kaum kolonis, yakni sistim pendidikan yang berdasarkan kebudayaan masyarakat sendiri. Di masa-masa dahulu, sebagai rakyat yang merdeka, orang Indonesia telah mempertahankan sistim pendidikannya sendiri dalam asrama, pondok dan pesantren.
Gagasan-gagasan baru pendidikan telah muncul, yang berakar pada “kemerdekaan dan “idealisme”, yang hadir sebagai reaksi atas pendidikan berdasarkan “paksaan” yang menganggap manusia sekedar komponen mesin dan menganggap penting “intelejktualisme” yang hanya memajukan “keduniawian” dan “materialisme” belaka. Gagasan Montessori dan Tagore, misalnya, perlahan bisa dianggap sesuai dengan sistim pendidikan nasional, dan sesuai gagasan Jawa tradisional tentang among, gagasan membimbing anak bukan dengan memberi mereka perintah-perintah, sehingga mereka bisa tumbuh sehat badan dan jiwanya.
Implementasi pendidikan nasional memerlukan kemerdekaan sebebas-bebasnya. Sehingga tak boleh diterima bantuan dari siapapun, sebab bisa berupa kekangan lahir dan batin. Agar bisa berdiri sendiri, Taman siswa mengadakan sistim swasembada yang berdasarkan “kehematan”.
Pendidikan harus untuk semua orang, bukan cuma untuk kalangan atas. Jika pendidikan hanya untuk kalangan atas, bangsa tak akan tumbuh kuat. Pendidikan harus dimulai dari bawah, penyebaran dikalangan itu paling diperlukan, supaya bangsa menjadi lebih tertib dan kuat.
Itulah sepotong kisah tentang pria hebat berkacamata. Salah satu tokoh pergerakan nasional, perintis penyelenggaraan pendidikan bagi kaum boemipotra melalui Sekolah Taman Siswa, dan tentu Bapak Pendidikan Nasional.
Beliau lahir di Yogyakarya pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Lalu dengan kesadaran penuh mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara guna mendekatkan diri dengan rakyat yang dicintainya.
Jelang usia genap 70 tahun, beliau dipanggil kembali kepangkuan Sang Pencipta pada 26 April 1959. Meninggalkan segenap gagasan-gagasan besarnya yang radikal tentang pendidikan yang memerdekakan, memanusiakan manusia, berorientasi kepentingan nasional, serta berpijak pada sistim kebudayaannya sendiri yang menjadi daya hidupnya.
Kemudian Presiden Sukarno melalui surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959 menetapkannya sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional.
Dan pada tanggal 16 Desember 1959, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur, menetapkan tanggal 2 Mei, yang dinisbatkan pada tanggal kelahirannya, sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebuah penghargaan yang memang pantas bagi tokoh besar dan inspiratif seperti dirinya.
Salam Anak Nusantara