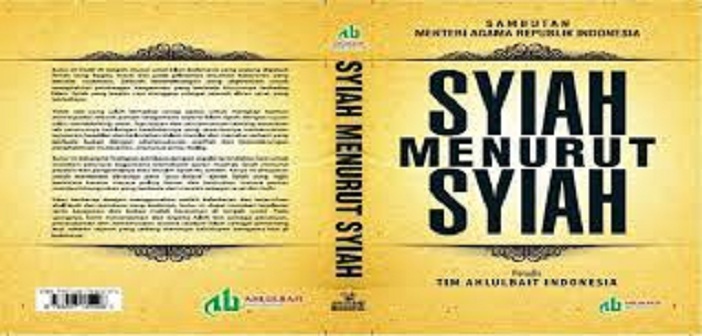Toni Ervianto, Alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen, Universitas Indonesia
Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam masalah agama adalah suatu kenyataaan yang tak terbantahkan. Hal itu karena pada qodratnya manusia berbeda-beda secara fisik maupun non fisik termasuk tingkat kecerdasannya. Sangat boleh jadi perbedaan-perbedaan itu telah termaktub dalam “buku induk” Lauhil Mahfuzh sebagai skenario ilahi untuk menjaga kehormatan manusia sebagai ciptaan terbaik-Nya.
Kita lihat Al Qur’an tidak hanya mengandung yang tegas siap pakai (muhkamat), tetapi juga ayat-ayat mutasyibihat yang multitafsir yang memungkinkan orang berbeda satu sama lain.
Menurut Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin dalam sambutan buku ini menyebutkan umat Islam di Indonesia yang berlatar belakang suku, adat istiadat dan bahasa yang berbeda-beda, tersusun dalam bangunan sosial yang potensial bisa retak. Ini disebabkan antara lain karena masih ada dari mereka yang terlalu terbenam dalam kesadaran masa lalu, dan dalam waktu bersamaan tidak mengembangkan karya-karya baru yang lebih inovatif sesuai konteks tempat dan waktu. Tidak mengherankan kalau diantara mereka yang melihat sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah dianggap sebagai buatan manusia belaka sebagai Pancasila dan NKRI adalah kreasi bangsa karena adanya kebutuhan mendesak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi perintah agama. Demokrasi juga demikian, dianggap pemerintahan kafir. Padahal pemerintahan berbasis rakyat diadakan karena kebutuhan mendesak menghindarkan mudlarat yang lebih besar yang ditimbulkan dari pemerintahan bentuk lain (Halaman ii).
Gerakan menegakkan “kedaulatan Allah” dari mereka yang belakangan kita ketahui dari kalangan Khawarij ini akhirnya terpuruk dalam lembaran hitam sejarah. Tidak heran kalau Sang Khalifah pembelaan Islam ala Khawarij ini sebagai Kalimatu al-haqq wa urida bihi al-bathil (kebenaran yang dipakai untuk membungkus tujuan bathil).
Dalam buku yang ditulis Tim Ahlulbait Indonesia ini, ditegaskan bahwa masyarakat Ahlulbait Indonesia (Syiah) menjadi yang terdepan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya dengan melakukan silaturahmi, membangun komunikasi yang sepadan dan beradab dengan semua lapisan masyarakat, serta memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah, insaniah, watania-yang diyakini sebagai pesan Allah SWT dalam Al Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (halaman x).
Buku ini ditulis dengan satu tujuan yaitu menawarkan sudut pandang alternatif tentang Syiah, sebagai bahan komparasi bagi orang-orang yang mungkin telah memperoleh atau diberi informasi tentang Syiah dari perspektif tertentu. Singkatnya, buku ini tidak mengajak pembaca untuk berpindah mazhab tapi mengajak setiap manusia rasional untuk menikmati keyakinannya sendiri sembari menghargai keyakinan orang lain dengan bekal informasi yang berimbang dan terbebaskan dari penafsiran pihak ketiga yang menyalahpahaminya.
Dalam buku “Syiah Menurut Syiah” juga digambarkan bagaimana ketidaksukaan Syiah terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terutama MUI Sampang dan MUI Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah adalah ajaran sesat. Menurut kelompok Syiah, fatwa MUI tersebut akan membawa dampak yaitu mendorong masyarakat Muslim ke dalam arena destruksi horisontal, konflik sektarian dan runtuhnya kebhinekaan (halaman 1). Tanpa memberikan hak jawab secara proporsional kepada Syiah atas tuduhan terhadap mereka dinilai orang Syiah sebagai rajm bi al-ghaib atau dalam bahasa populernya adalah pengadilan in-absentia (halaman 11).
Dalam buku ini, juga digambarkan dengan jelas bahwa pola pikir orang Syiah yang memiliki konsep pemikiran dengan prinsip “dahulukan apa atas siapa”, “dahulukan komparasi atas mindset”, “dahulukan mayor atas minor”, “dahulukan kualitas atas kuantitas”, “dahulukan validitas atas utilitas”, “dahulukan logika atas teks”, “dahulukan sebab atas akibat”, “dahulukan subyek atas obyek”, “dahulukan fakta atas opini”, “dahulukan substansial atas formal”, “dahulukan konsep atas realitas”. (halaman 11). Kelompok Syiah juga membantah mereka menuhankan Ali, karena faktanya Syiah hanya mengutamakan Ali diantara sahabat Nabi lainnya (halaman 11).
Kelompok Syiah juga menilai bahwa mereka yang mengkritik dan menuduh Syiah sebagai aliran sesat tidak mencerminkan Islam, karena akar kata yang membentuk kata “Islam” ada empat yang berkaitan satu sama lain yaitu aslama artinya menyerahkan diri, salima artinya selamat, sallama artinya menyelamatkan orang lain dan salam artinya aman, damai dan sentosa (halaman 27).
Buku ini juga menjelaskan bahwa agama wahyu yang dibawa oleh Muhammad putra Abdullah Saw ini secara prinsip tidaklah berbeda jauh dengan dua agama wahyu sebelumnya : Yudaisme dan Kristianisme. Perbedaan yang mencolok adalah terletak pada prinsip keesaan (monoteisme) dan prinsip kenabian. Bagi Muhammadisme, siapapun selain Tuhan Swt, tidak layak dianggap sebagai Tuhan, anak Tuhan, menjelmakan Tuhan atau menjadi tumbal Tuhan, meskipun sebagian agamawan Kristen memberikan makna metafora untuk kata anak. Bagi Muhammadisme, Moses (Musa) dan Yesus (Isa) adalah para pewarta dan penerima wahyu Ilahi yang agung dan mulia, namun nabi pamungkas, termulia dan teragung adalah Muhammad SAW (halaman 27).
Terkait Sunni dan Syiah, buku ini menerangkan bahwa Sunni dan Syiah adalah dua persepsi relatif yang terstruktur tentang mekanisme mendekati wilayah kesucian. Keduanya bukan agama melainkan interpretasi terhadap agama. Keduanya hanyalah mazhab. Sunni dan Syiah sama-sama memahami adanya penghubung antara umat dengan Nabinya, karena Nabi adalah seorang yang mutlak benar. Persoalannya adalah ada orang-orang tertentu yang menolak hukum relativitas ini, baik implisit maupun eksplisit, dengan mengatakan bahwa apa yang dipahaminya tentang Al-Qur’an dan Al-Hadist itu persis sebagaimana yang diterima oleh Nabi. Hal ini terjadi baik di kalangan Sunni dan Syiah, karena kesadaran adanya relativisme ini dihilangkan, sehingga muncullah fanatisme dan ekstremitas. Syiah tidak menjalankan hadis terkenal “ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah sesudahku”, bukan karena tidak mempercayai khafilah pengganti nabi, namun hadist ini berkonsekuensi logis turunnya pangkat kenabiaan atau naiknya pangkat kekhalifahan, artinya tingkatan seorang nabi tidak bisa digantikan oleh siapapun dari umatnya yang tidak suci. Baik Sunni maupun Syiah, yang sama-sama bukan sahabat dan bukan imam, tidak perlu saling bersikeras. Yang Sunni bukan sahabat Nabi, sehingga tidak memiliki konsekuensi “adil”, dan yang Syiah juga bukan imam, yang tidak memiliki konsekuensi suci, karena sama-sama tidak memiliki keadilan dan kesucian, maka Sunni dan Syiah sama-sama tetap relatif (halaman 31).
Kesimpulan buku ini adalah reinterpretasi konsep kepemimpinan setelah Nabi tidak meredusir konsep Khilafah yang umum diyakini oleh kalangan mainstream Sunni dan tidak pula mendistorsi substansi kepemimpinan I mamah yang dipegang teguh oleh kalangan Syiah. Kalangan Sunni secara de facto menerima kepemimpinan esoterik Ali dan Ahlulbait, sebagaimana terkonfirmasi melalui ragam riwayat dalam referensi-referensi utamanya, terutama di kalangan sufi. Sementara kalangan Syiah secara de facto menerima kepemimpinan esoterik Khilafah yang diusung oleh Sunni, yang dimulai dari Abu Bakar. Menjadi Sunni atau Syiah bukanlah kesalahan. Seorang Muslim yang dibentuk karena asas ketauhidan dan kerasulan Muhammad sebagaimana termaktub dalam dua kalimat syahadat, harus menafsirkan dua konsep kepemimpinan, Khilafah dan Imamah sebagai konsekuensi dari dua perspektif yang berbeda (halaman 356).
Para pemikir dari Sunni dan Syiah harus mengubah energi gontok-gontokkan menjadi energi saling mendukung dan membahu mencerdaskan akar rumput dan awamnya serta membuat semua isu elementer yang menjadi biang kebencian mutual. Kalangan Sunni harus rela memosisikan para khalifah dan sahabat sebagai manusia yang tidak sempurna, yang bila tidak diyakini kekhalifannya tidak berarti keluar dari Islam. Kalangan Syiah perlu makin aktif menegaskan kepatuhan dan kecintaan kepada imam tidak bersifat primer, karena itu merupakan konsekuensi dari kepatuhan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan bahwa orang yang tidak memosisikan mereka sebagai imam tidak menyebabkannya keluar dari Islam (halaman 357).
Peresensi melihat sebaiknya dibangun komunikasi dan silaturahmi antara kelompok Syiah dan Sunni, karena menilik pendapat almarhum Gus Dur bahwa sebenarnya Syiah itu adalah Sunni tapi yang memakai cara imamah. Umat Islam juga jangan mudah “terprovokasi” dengan kelompok lainnya yang akan membenturkan Syiah dan Sunni, karena tidak mustahil kelompok tersebut mengadopsi pemikiran sosiolog Inggris, Hampers yang berusaha memisahkan agama dan negara, dalam rangka memecahbelah Islam, bahkan konon Hampers-lah yang merekrut kelompok Wahabi Takfiri untuk menghancurkan Islam dengan menggunakan isu Syiah sebagai isu antara saja, sehingga dibalik ini semua umat Islam harus menyadari adanya “proxy war” yang dimainkan pihak ketiga.
Facebook Comments