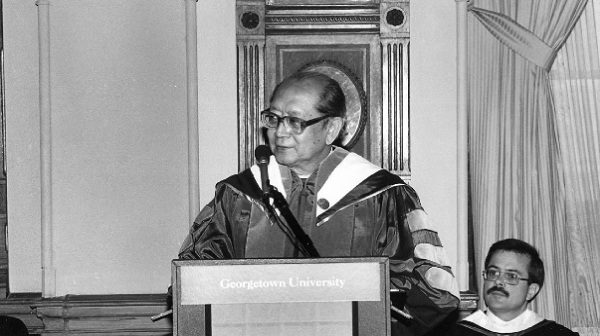Seorang Duta Besar mengirimkan laporan berkala atau suatu masalah khusus kepada Menteri Luar Negeri, memang merupakan suatu hal yang umum dan bersifat rutin. Namun bila seorang Duta Besar secara teratur dan berkesinambungan mengirim laporan secara langsung kepada Presiden dalam bentuk surat-surat pribadi, maka hal itu harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa dan di luar kelaziman diplomatik. Namun Dr Soedjatmoko, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada 1968-1971, memang bukan Duta Besar biasa.
Melalui surat-surat pribadinya kepada Presiden Suharto, Pak Koko, begitu sapaan akrab kepada esksponen Sekolah Tinggi Kedokteran Ika Daigakudan pentolan Komunitas Mahasiswa Prapatan-10 itu, telah mendokumentasikan pemahamannya yang mendalam dan analisis-analisisnya yang tajam mengenai pelbagai masalah politik dan keamanan internasional, khususnya di Asia Tengara, pertumbuhan Non-Blok dan lain sebagainya.
Lingkup tinjauan dan analisisnya tidak sebatas pada aspek-aspek hubungan kerjasama pembagunan Indonesia-AS, melainkan juga terkait hubungan RI dan IMF, Bank Dunia dan IGGI. Pula termasiuk perkembangan dan kecenderungan perekonomian internasional. Selain analisis-analisi, juga dilengkapi pula dengan usulan dan saran tindak konkrit. Melalui surat-surat pribadinya kepada Pak Harto, tergambar jelas betapa Pak Koko memang mempunyai kedalaman analisis dalam bidang sosial-politik sekaligus seorang pemikir strategis.
Pada periode 1966-1971, Pemerintahan Suharto sedang melakukan konsolidasi kekuasaan yang kelak dikenal dengan nama Orde Baru. Program utama dari pemerintahan yang baru terbentuk itu adalah Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi (Rehabilitasi Ekonomi).
Alhasil, kebijakan strategis perekonomian nasional kala itu difokuskan untuk mendorong investasi dan bantuan asing. Sehingga pemerintah terpaksa membuka diri terhadap investasi dari negara-negara barat, suatu kebijakan yang justru ditentang oleh Presiden pertama RI Sukarno. Konsekwensi logis dari hal itu, pemerintahan Suharto banyak memberikan kemudahan bagi Barat, dan bahkan menandatangani suatu perjanjian dengan AS untuk memberikan jaminan bagi para investor AS. PT Freeport McMoran, sekadar ilustrrasi, merupakan salah satu contoh sebuah korporasi yang diuntungkan dari pergeseran orientasi ekonomi-politik yang dilakukan Presiden Suharto.
Singkat cerita, pemerintahan Suharto berupaya mendekat pihak Barat dan Jepang, termasuk negara yang pernah menjajah kita, Belanda. Untuk mengorganisir negara-negara donor membantu Indonesia. Maka, pada 1967 enam negara donor kemudian membentuk Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Keeenam negara donor tersebut adalah: AS, Jepang, Belanda, Jerman, Inggris dan Australia. Dari keenam negara itu, AS dan Jepang merupakan negara-negara donor terbesar.
Dan Soedjatmoko, perannya menjadi strategis mengingat jabatannya sebagai Duta Besar AS ketika itu. Begitupun, menarik, menyimak suratnya kepada Pak Harto tertanggal 26 Mei 1969:
“Di dalam menunaikan tugas saya sebagai Duta Besar di sini (AS), dari semula tujuan pokok yang dikejar adalah tiga: Pertama, maksimalisasi pemindahan dana, baik dari pemerintah maupun swasta, dari Amerika Serikat ke Indonesia. Kedua, sebanyak-banyaknya mempengaruhi kristalisasi konsepsi-konsepsi baru mengenai bantuan luar negeri. Ketiga, sedapat-dapatnya mempengaruhi konsepsi-konsepsi baru mengenai peranan strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara, sehingga sesuai, atau setidak-tidaknya, tidak berlawanan dengan kepentingan nasional Indonesia.”
Bahkan melalui surat Pak Koko kepada Pak Harto tertanggal 16 Juni 1968, jadi sekitar setahun sebelum suratnya yang tertanggal 26 Mei 1969, nampak tergambar jelas jalan pemikiran para perancang strategis AS di Washington mengenai agenda tersembunyi AS di balik komitmennnya untuk mengorganisir negara-negara donor secara multilateral dalam mendukung Indonesia:
“Pihak pemerintah Amerika sudah pasti dalam keyakinannya bahwa Pemerintah Suharto ini harus berhasil agar supaya Indonesia dapat berkembang ke arah non-komunis, dan agar supaya potensi Indonesia dapat dimanfaatkan, baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk bangsa-bangsa lain di dunia. Di samping itu, dia (AS) melihat Indonesia sebagai sangkar untuk setiap usaha kea rah pembinaan stabilitas di Asia Tenggara. Atas dasar ini, dia bersedia untuk memberi bantuan kepada Indonesia. Adapun besarnya dan cepatnya bantuan itu disampaikan kepada Indonesia, ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan.
….Amerika hendak memberi bantuan itu dalam suatu rangka multilateral dan oleh kesanggupan daripada negara-negara lain turut serta.”
Pandangan yang disampakain Pak Koko dalam membaca jalan pemikiran para penentu kebijakan luar negeri AS itulah, yang nampaknya merupakan landasan terbentuknya IGGI seperti yang kita ketahui kemudian.
Tapi, sedari awal bantuan luar negeri pihak Barat dan Jepang ini telah mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan nasionalis di Indonesia. Pertama, model bantuan luar negeri seperti ini tidak akan menguntungkan negara-negara penerima, bahkan sebaliknya justru menjadi pembuka jalan bagi perusahaan-perusahaan raksasa Amerika dan Eropa untuk menerapkan kebijakan Neo-Kolonialisme secara halus lewat skema bantuan ekonomi.
Kedua, bantuan luar negeri semacam ini, pada kenyataannya hanya masuk dalam kantong para elit politik di negeri-negeri miskin yang semuanya korup. Beberapa kasus yang terjadi selama era Orde Baru pemerintahan Suharto hingga kejatuhannya pada Mei 1998, memang membenarkan pandangan-pandangan kritis tersebut. Betapa bantuan luar negeri sejatinya telah menghilangkan rasa kepercayaan diri dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa merdeka.
Menyadari adanya gelombang aspirasi berbagai elemen strategis masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan kaum intelektual yang skeptis terhadap bantuan asing, Soedjatmoko meski menjabat sebagai Duta Besar RI di AS, namun karakternya sebagai seorang cendekiawan tetap tidak bisa dihindarkan. Koko, dalam suratnya kepada Pak Harto tertanggal 2 Januari 1971, mengingatkan Presiden kedua RI tersebut agar kita jangna sampai tergantung pada utang luar negeri. Pak Koko menulis:
“Kiranya pemerintah akan harus menggariskan sebagai kebijaksanaannnya bahwa Indonesia tidak bermaksud untuk selalu tergantung dari bantuan luar negeri, malahan berusaha untuk mengurangi pada suatu waktu dan akhirnya mengakhiri ketergantunganya dari bantuan luar negeri. Dengan jalan meningkatkan kemampuan Indonesia sendiri. Usaha sendiri yang lebih besar ini memerlukan agaknya suatu kampanye di tiga bidanbg: Pertama, memperbesar public saving. Kedua, memperbesar private saving dan private investment. Dan ketiga, memperbesar ekspor.”
Agaknya, melalui beberapa surat pribadinya itu, Soedjatmoko sedikit banyak merefleksikan upaya dari berbagai elemen strategis bangsa di masa transisi dari era Sukarno ke era Suharto, yang sedang meraba-raba bagaimana menjalankan dan mempertahankan politik luar negeri bebas aktif dalam situasi baru yang oleh karena tekanan-tekanan berbagai masalah dan krisis perekonomian nasional, terpaksa berpaling ke negara-negara Barat dan Jepang.
Memandang dari segi ini, kurun waktu penugasan Soedjatmoko sebagai Duta Besar RI antara 1968-1971 merupakan merupakan masa peralihan yang amat menentukan dalam hubungan Indonesia-Amerika. Sehingga kedudukan dan peran Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang berpenduduk terbesar, memiliki sumber-sumber daya alam yang beraneka ragam, dan letak geopolitiknya yang amat strategis dan menganut paham politik luar negeri bebas dan aktif, benar-benar dalam ujian di kurun waktu itu.
Betapa tidak. Pada 1967, Indonesia berhasil memotori terbentuknya Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melalui Deklarasi Bangkok. Namun pada saat yang sama beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Singapura, Malaysia dan Thailand, semuanya terikat perjanjian pertahanan militer dengan Amerika Serikat dan Inggris. Sementara Indonesia, sebagaimana di era Sukarno, masih tetap berkomitmen untuk secara taat menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Namun di waktu yang sama pemerintahan Suharto justru mengandalkan diri pada bantuan ekonomi dari AS dan negara-negara Barat maupun Jepang melalui skema IGGI.
Begitupun, di situlah pula nilai strategis Indonesia di mata AS memang cukup tinggi dan amat diperhitungkan sebagai negara besar di Asia. Sehingga dalam pandangan Washington, dalam membangun stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, peran penting Indonesia menjadi mutlak adanya.
Bagi AS, Indonesia juga dipandang penting baik dari segi strategi ekonomi dan militer, karena 46 persen pasokan bahan bakar dari Timur Tengah ke Jepang harus melalui selat-selat kepulauan Indonesia. Pertautan erat kepentingan ekonomi AS dan Jepang, dan oleh karena Jepang secara politik,ekonomi, dan militer merupakan jangkar dari keseluruhan palung persekutuan AS di Asia Pasifik (Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Filipina, sampai dengan Australia dan Selandia Baru), maka dengan sendirinya letak dan nilai strategis Indonesia menjadi semakin diperhitungkan oleh Washington maupun Tokyo.
Menyelami pandangan Pak Koko melalui suratnya kepada Pak Harto tadi, tersirat bahwa dukungan AS untuk memotori terbentuknya bantuan ekonomi secara multilateral melalui Skema IGGI, memang bukan bantuan yang bersifat gratisan alias Cuma-Cuma. Di di dalam skema bantuan IGGI tersebut, terkandung tujuan-tujuan stategis untuk menarik Indonesia dalam orbit pengaruh negara-negara Barat dan Jepang, yang ketika itu merupakan sebuah kutub berhaluan kapitalisme-liberal melawan kutub komunis Uni Soviet dan Cina.
Dalam beberapa laporan dan analisisnya mengenai perkembangan global maupun kontalasi politik internasional di tengah memanasnya Perang Dingin kedua kutub tersebut, terungkap betapa di mata AS Indonesia memang punya nilai strategis yang cukup tinggi sebagai negara yang amat diandalkan untuk memelihara stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sedemikian tingginya, bahkan melebihi nilai Filipina yang notabene memang merupakan sekutu strategis dan tradisional AS di Asia Tenggara.
Soedjatmoko dalam salah satu suratnya mengisahkan, betapa Filipina, sebagai sekutu utama AS yang dianggap setia, merisaukan tingkat bantuan militer AS yang diarahkan kepada Indonesia (20 Juta dollar), melebihi yang diberikan kepada Filipina yang hanya 17 Juta dollar.
Maka, sungguh tepat dan jitu Dr Juwono Sudarsono, ketika mengulas isi surat-surat pribadi Koko kepada Pak Harto, yang kemudian dibukukan dengan judul: Surat-Surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal) Soeharto. Dalam ulasannya Juwono Sudarsono menulis, betapa pekanya Koko membaca gelagat ekonomi dan politik dunia dalam ikut mempengaruhi perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia dalam membangun stabilitas Asia Tenggara.
Selain itu, Koko juga cukup jeli dan peka dalam melihat perkaitan antara masalah-masalah perimbangan strategis militer Amerika-Soviet di Eropa, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan segitiga Amerika-Jepang-RRT serta keinginan pemerintah Jepang untuk lebih berperan lagi dalam bidang ekonomi dan investasi di Asia Tenggara.
Menariknya, berkat kejelian dan kepekaannya dalam membaca konstalasi global maupun dalam melihat perkaitan masalah-masalah global dengan regional, regional dengan nasional, nasional dengan provincial, dan provincial dengan lokal, Koko kemudian mengajukan beberapa usulan strategis kepada Suharto yang tentunya punya implikasi strategis baik dari segi Politik-Keamanan maupun ekonomi terhadap negara-negara adikuasa yang sedang bertikai dalam Perang Dingin tersebut.
Seperti tergambar melalui salah satu suratnya, Soedjatmoko sempat menyarankan Suharto agar kelanjutan proyek pabrik baja Cilegon ditangani dengan cermat, Sarannya kepada Pak Harto, agar pemulihan proyek Cilegon ditawarkan dahulu kepada Uni Soviet untuk mengatasinya sebelum ditawarkan kepada calon penanam modal dari negara-negara Barat atau Jepang.
Menurut pertimbangan Soedjatmoko kepada Presiden Suharto, langkah ini penting dilakukan untuk menghormati harga diri Uni Soviet, untuk menjaga citra Indonesia sebagai negara yang bebas dan aktif, tetapi juga untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berhadapan dengan investor negara-negara Barat dan Jepang.
Dalam bagian lain dari surat Koko kepada Pak Harto, tertanggal 4 Februari 1969, pria yang pada 1980 terpilih sebagai Rektor Universitas PBB di Tokyo itu, nampaknya melihat suatu tren yang jauh lebih strategis, terkait peran kehadiran Uni Soviet menyusul keberhasilan Vietnam mengusir Perancis pada 1954.
Koko menulis:
“Dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun sesudah Perang Vietnam (karena surat ini ditulis pada 1969, berarti konteksnya adalah ketika Vietnam mengusir Perancis sebagai penjajah, bukan ketika Vietnam Utara berhasil mengusir AS dari Vietnam Selatan), kita akan harus memperhitungkan adanya suatu presence (kehadiran) kekuatan Uni Soviet di Asia Tenggara. Sekarang gerak ke arah itu sudah mulai tampak. Uni Soviet akan mendirikan Kedutaan Besr di Singapura, di Kuala Lumpur dan juga bermaksud untuk mengadakan suatu perwakilan di Filipina, Di samping itu, secara sistematis Rusia sekarang membeli karet yang dahulu dibeli di pasaran Eropa langsung dari Singapura.
Perkembangan-perkembangan ini, agaknya menunjukkan keinginan Uni Soviet untuk berkelakuan sebagai suatu kekuatan dunia, suatu world power, yang secara otomatis hendak mengisi semua vacuum kekuasaan di dunia ini, dan yang hendak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, lepas daripada ideologi pemerintahannya.
Dalam amatan Koko yang jeli dan tajam, landasan terpenting dari kehadiran Soviet di Asia Tenggara nanti (berarti dalam proyeksi Soedjatmoko akan terjadi pada 1974-1979), ialah hubungannnya dengan Vietnam Utara. Bahkan dalam amatan Koko pada 1969, Soviet sudah memainkan peran penting di Vietnam Utara melalui bantuannya yang amat besar di bidang ekonomi dan militer.
Strategi bagaimana memperkuat posisi tawar Indonesia menghadapi Jepang, nampaknya merupakan salah satu segi lain yang tak kalah menarik dari rangkaian surat-surat pribadi Koko kepada Pak Harto. Gagasa dasar Koko adalah, Indonesia jangan hanya mengandalkan good will atau niat baik Jepang semata dalam memperoleh bantuan Jepang. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperkuat bargaining position Indonesia terhadap Jepang.
Maka inilah saran Koko kepada Pak Harto dalam Suratnya 22 Desember 1969:
“Dari Washington ini, saya tidak bisa melihat semua segi daripada persoalan ini. Tapi sudah barang tentu bahwa segala usaha untuk memperkuat ASEAN, untuk memperluas ASEAN, dan untuk mempertegas peranan Indonesia dalam lingkungan ASEAN itu, akan memperkuat posisi tawar-menawar kita terhadap Jepang. Pada pokoknya, persoalan yang kita hadapi dalam hubungan dengan Jepang ini serta kemampuannya, baik untuk memberi bantuan kepada, atau untuk menguasai, Asia Tenggara, ialah secara bagaimana kita bisa menerima bantuan yang lebih besar dari Jepang, tanpa menjual diri kepada Jepang. Tidak ada jeleknya, agaknya, jikakalau diadakan studi khusus untuk meninjau ‘Japan Policy’ kita dalam hubungan ini.”
Hikmah dari kisah tentang kiprah Soedjatmoko sebagai Duta Besar RI di AS, hendaknya dapat mengilharmi para stakeholders (pemangku kebijakan luar negeri RI). Khususnya bagi setiap warga bangsa yang mewakili Indonesia di mancanegara. Baik sebagai pejabat negara maupun sebagai warga negara biasa.
Pertama, betapa pentingnya para pemimpin negara kita memanfaatkan letak geopolitiknya untuk memajukan kepentingan nasional.
Kedua, hendaknya para pemimpin negara kita mampu secara cermat membaca perobahan-perobahan mendasar yang mempengaruhi letak geopolitiknya itu, sehingga ia dapat meraih selisih-selisih keunggulan dari perobahan cepat di bidang ekonomi maupun ilmu dan teknologi.
Melalui surat-surat pribadi kepada Presiden Suharto, terungkap bahwa kedua faktor dasar tersebut selalu dalam benak Soedjatmoko sebagai wakil dari bangsanya yang sedang mencari jalan keluar dari kemelut politik ekonomi dan sosial.
(Diolah dari Buku bertajuk Surat-Surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal Soeharto, 16 Juni 1968-26 April 1971), Diterbitkan atas kerjasama Yayasan Soedjatmoko dan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002).
Penulis: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
Facebook Comments