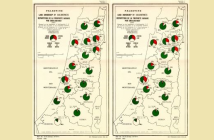Tatkala UUD 1945 diamandemen empat kali (1999-2002) oleh National Democratic Institute (NDI) pimpinan Madane Albright bersama para operator lokalnya (proxy agents), maka semenjak itulah demokrasi kita berubah liberal. Apa hendak dikata. Demokrasi Indonesia kini modelnya: ‘satu orang satu suara’ (one man one vote). Suara seorang profesor disamakan dengan suara mahasiswa; suara mantan presiden sama dengan suara (maaf) sopir angkot. Itulah Demokrasi Langsung yang menafikan nilai-nilai Musyawarah Mufakat sebagaimana termaktub di sila ke-4 Pancasila:
“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan“.
Salah satu poin urgen dalam Sidang Paripurna DPD RI, 14 Juli 2023, menyebut bahwa praktik UUD NRI 1945 Produk Amandemen (1999-2002) telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Ini temuan ironi. Vivere pericoloso. Manakala philosophische grondslag sebuah negara diabaikan dengan sengaja, akan muncul berbagai implikasi negatif dalam proses bernegara, karena menyalahi takdir geopolitik. Salah satunya, misalnya, meski tidak secara formal, bahwa praktik demokrasi berbasis UUD Produk Amandemen kerap diistilahkan para pegiat konstitusi sebagai Demokrasi Perjudian alias Demokrasi 303. Guyon parikeno. Ya. 303 adalah pasal di KUHP tentang perjudian yang sifat dan unsurnya untung-untungan. Demokrasi undian.
Bagi kelompok pemuja dan penikmat Demokrasi 303 ini, siapa yang berharap besar pada demokrasi semacam ini harus merangkul alias merapat ke ‘bandar’. Kalau tidak, ya kalah melulu!
Mengapa begitu? Selain perlu dana besar, juga algoritma perjudian dimanapun selalu memenangkan si bandar daripada unsur lainnya. Atau paling minimal, agar ‘posisi aman’ dalam dinamika Demokrasi 303 ini, salah satu jalan pintasnya melalui cara mem- buzzer-kan diri sebagai kelompok hore. Modalnya pun simpel, selain berbekal lidah tak bertulang, juga berani menelan dogma tua buzzer yakni “Ketika tulang ada di mulut anjing, maka kebenaran hanya milik sang tuan”. Menyedihkan.
Jujur. Demokrasi semacam ini, selain ongkosnya mahal, juga mengabaikan integritas, tak perlu kapasitas, tidak membutuhkan kapabilitas. Yang penting popularitas, elektabilitas, dan ‘isi tas’.
Kenapa demikian?
Sebab, yang dikejar para kontestan hanyalah vote. “Banyak-banyakan suara”. Menjaring sebesar-besarnya pemilih. Inilah pola pencarian pemimpin secara kuantitas baik dalam Pilpres maupun di Pilkada, bukan secara kualitas (Baca: Indonesia dalam Keadaan Bahaya Akibat Demokrasi ala Taman Kanak-Kanak).
Namun, bagi yang memahami situasi dan kondisi secara totalitas (komprehensif integral), Demokrasi 303 ini mutlak harus dihentikan, kenapa? Ya. Melanjutkan demokrasi model begini identik dengan mengijon masa depan bangsanya kepada kelompok bandar (Baca: Menjual Harapan, Mengijon Masa Depan).
Bagaimana modus menghentikannya, yakni dengan cara ‘membalik meja judi’ para bandar. Apa boleh buat. Pertanyaannya sederhana, “Bagaimana mungkin mempertaruhkan nasib bangsa di meja judi, sedang algoritma perjudian berpihak kepada bandar?”
Namanya juga judi, pas lagi beruntung mungkin terpilih yang masih memiliki kapasitas, integritas, intelektualitas dan lain-lain. Tapi, coba bayangkan (dan sungguh celaka) bila yang terpilih ialah sosok yang cuma berbekal popularitas dan isi tas. Kenapa? Karena kelak, setiap kebijakan yang terbit niscaya dalam kendali segelintir orang yang memiliki ‘isi tas’. Inilah yang kerap disebut oligarki ekonomi. —kelompok pemodal— atas nama politik transaksi dan kebijakan balas budi.
Prof Amien Rais (AR) —tokoh reformis— contohnya, beliau mengaku kapok. Menyesal atas kenaifan sewaktu menjadi Ketua MPR RI. Dulu, AR berprasangka bahwa dengan amandemen UUD 1945 serta digantinya model Pilpres di MPR menjadi Pilpres secara langsung (one man one vote), sangat mustahil bagi para pemodal mampu menyuap (money politic) sampai ratusan juta pemilih. Namun, prasangka si tokoh reformis itu menyesatkan. Praktiknya ternyata bisa, mampu dan terjadi. Bahkan, sejak Pilpres Langsung dekade 2004-an silam, isu money politics dan aneka modus sejenis justru berlangsung masif, sistematis, bahkan terstruktur.

Balik ke laptop. Nah, persepsi dan konsep ‘membalik meja judi’ dalam Demokrasi 303 sebenarnya sudah disosialisasikan ke publik oleh para pegiat konstitusi melalui gerakan kembali ke UUD 1945 dengan beragam metode. Banyak tokoh terlibat di dalamnya, seperti Taufiequrachman Ruki dkk lewat buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945; atau Prijanto melalui Dekrit Terkoordinasi, dr Zulkifli Ekomei, Hatta Taliwang, dan pegiat lain secara silent melalui forum diskusi/seminar.
Yang fenomenal justru gerakan dari internal yang diprakarsai oleh LaNyalla Mattalitti, Ketua DPD RI. Ya. Perubahan dari sisi dalam. Ibarat telor. Konon perubahan dari dalam akan menghasilkan kehidupan baru yang lebih baik (lahir piyek, anak ayam) daripada perubahan dari luar yang cenderung ‘pecah’.
Bahkan kemarin, gerakan LaNyalla menular ke Bambang Soesatya (Bamsoet), Ketua MPR RI meski kemasannya agak berbeda. Bamsoet melakukan safari ke tokoh-tokoh nasional di antaranya ialah Pak Try Soetrisno, Prof AR, Jusuf Jalla dan seterusnya dengan misi agar konstitusi kedepan, terutama Pilpres dikembalikan di MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, lalu dihidupkan lagi PPHN (dulu: GBHN).
Tak boleh dipungkiri, gerakan kembali ke UUD 1945 bukanlah gerakan politik praktis, namun lebih kepada gerakan moral kebangsaan dalam rangka mengembalikan jati diri bangsa yang dulu berwajah guyub, rukun, tepa selira, toleransi, cinta damai, gotong royong dan lain-lain. Namun, sejak menganut Demokrasi 303 yang berbasis UUD NRI 1945 Produk Amandemen, wajah bangsa kini berubah intolerans, beringas, individualis, suka kegaduhan, mudah diadu-domba dan lain-lain. Lihat saja, baru ditebar isu receh Nasab Habaib saja, umat mayoritas seketika gaduh lagi terbelah. Tengok saja, disebar isu Vina, kasus korupsi timah (Rp 300 Triliun) langsung tenggelam, dan lainnya.
Mencermati gerakan kebangsaan di atas, tampaknya ada dua mazhab atau aliran yang berkelindan, antara lain:
1. Aliran Pertama. Kembali ke UUD 1945 melalui Amandemen ke-5. Mazhab ini menekankan pada pengembalian MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebab Pilpres nantinya akan digelar di MPR, dan juga dihidupkan lagi GBHN (PPHN) agar kebijakan pemerintah tidak reaktif (berbasis pesanan);
2. Aliran Kedua. Kembali ke UUD 1945 sesuai Naskah Asli dengan Teknik Adendum. Artinya, langkah awal aliran ini mutlak harus kembali dulu ke UUD asli. Titik. Bila kemudian perlu penyempurnaan akibat faktor perkembangan zaman, maka perubahan dilakukan melalui teknik adendum/lampiran/tambahan. Jadi, penyempurnaan tidak mengubah naskah asli. UUD 1945 karya agung Pendiri Bangsa tetap orisinil. Utuh.
Itulah dua mazhab perubahan konstitusi yang berkelindan santer di ruang publik. Pertanyaan kini, bukan aliran mana lebih kuat atau dominan, tetapi bagaimana jalan yang lurus untuk bangsa ini?
Realitanya ada dua mazhab perubahan konstitusi pada satu sisi, sedang di sisi lain, Partai Gerindra sendiri selaku ‘rumah asal’ Presiden Terpilih (Prabowo Subianto), memiliki agenda —AD/ART— untuk kembali ke UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Pas! Tidak ada yang kebetulan di muka bumi, bahkan selembar daun jatuh pun sudah tertulis di Lauhul Mahfudz.
Simpulan prematur pada catatan ini, jika ingin membalik meja judi para bandar Demokrasi 303 ialah dengan cara mengembalikan konstitusi kita sesuai rumusan the Founding Fathers sebagaimana tersurat dalam AD/ART Gerindra pada Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1). Adapun penyempurnaan UUD guna menyesuaikan lingkungan strategis yang berubah, dilakukan melalui teknik adendum.
Demikianlah adanya, demikian sebaiknya.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)