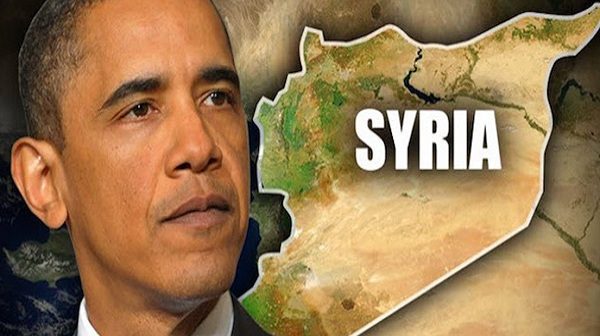Pengantar
Perkembangan terakhir di medan perang di Suriah menunjukkan bahwa pasukan pemerintah yang didukung oleh sejumlah milisi dan Angkatan Udara Rusia semakin menjepit posisi kelompok ISIS di Alepo. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa jalannya peperangan di bumi Syam itu mengalami perubahan signifikan menyusul gempuran AU Rusia terhadap sejumlah wilayah yang dikuasai ISIS. Kini, sebagian besar wilayah di negeri itu—yang sebelumnya diduduki oleh ISIS—telah jatuh ke tangan tentara pemerintah. Kelompok fundamentalis saat ini praktis tersudut di wilayah Alepo.
Dalam kondisi semakin terjepitnya ISIS itu para pemimpin AS dan Barat meminta agar segera didakan gencatan senjata kepada semua pihak. Alasan yang dikemukakan adalah agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat sipil Suriah yang bermukim di Alepo yang mungkin saja akan terkena akibat peperangan. Di satu sisi, alasan semacam ini boleh jadi ada benarnya. Namun di sisi lain, pernyataan para pemimpin AS dan Barat itu justru mengherankan dan memunculkan tanda tanya. Permintaan pemimpin AS dan Barat untuk gencatan senjata itu justru muncul di saat-saat terdapat momentum penting untuk menyapu bersih kaum teroris dari bumi Suriah semakin terbuka lebar.
Implikasi praktis dari apa yang dinyatakan oleh para pemimpin AS dan Barat itu justru dapat bermakna proteksi bagi kelompok ISIS yang tengah terjepit untuk mengkonsolidasikan kembali kekuatan militernya. Dari sisi ini, Rusia jelas tidak bodoh. Sekalipun Moskow secara terbula menyatakan setuju gencatan senjata dan penghentian permusuhan antar para pihak yang bertikai, namun kekuatan udaranya terus menghantam posisi ISIS di Alepo. Rusia berada dalam posisi: tidak ada damai dengan kaum teroris, sekalipun hanya sedetik.
Presiden Rusia Putin dan para koleganya di Moskow mengetahui secara persis bahwa permintaan AS dan Barat untuk segera menggelar gencatan senjata di Suriah tidak lebih dari upaya untuk memperpanjang sedikit napas yang masih tersisa dari milisi anti pemerintah. Dengan demikian, desakan untuk gencatan senjata itu merupakan strategi reposisi untuk kembali ke misi awal yang telah dicanangkan oleh AS dan Barat bersama kaum opsisi bersenjata di negeri itu: mendongkel Presiden Bashar Assad dari kursi kepresidenan.
Oleh karenanya, para pemimpin AS dan Barat terus melancarkan kritik atas apa yang mereka namakan sebagai “intervensi militer” Rusia atas Suriah yang kini telah semakin mengurung milisi anti pemerintah di Alepo. Dengan demikian, desakan gencatan senjata oleh AS dan Barat juga dapat bermakna mencegah agar milisi oposisi Suriah tidak disapu bersih oleh AU Rusia.
Lenyapnya kaum oposisi bersenjata di bumi Suriah akan membuyarkan seluruh skenario AS dan Barat untuk menjatuhkan Presiden Bashar Assad. Atau dengan kata lain, bagi AS dan Barat, kekalahan kaum oposisi—dengan kelompok ISIS sebagai inti kekuatannya—sama artinya dengan hilangnya “kartu” yang selama ini mereka mainkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Suriah menginginkan pemimpin baru sebagai pengganti Assad. Dalam konteks inilah, sikap AS dan Barat yang bersikeras mendesak gencatan senjata di Suriah itu diletakkan.
Gagal Memproyeksi
Dilihat dari sudut skenario awal AS dan Barat, perkembangan dan arah peperangan di Suriah dewasa ini jelas berada di luar perhitungan mereka. Alih-alih menjatuhkan Assad dari tampuk kekuasaannya, kondisi mutakhir peperangan di negeri ini sedikit-banyak justru merekonsolidasi pemerintahan Assad, sekurang-kurangnya dari segi militer. Harapan mereka untuk mempertontonkan sebuah pentas di mata dunia bahwa “rakyat” Suriah tengah melakukan “revolusi” untuk menjatuhkan Assad gagal dimainkan. Terdapat sejumlah faktor yang agaknya luput dari perhitungan para pengambil keputusan di Washington terkait dengan arah dan dampak perang di Suriah.
- Apa yang dinamakan kelompok oposisi bersenjata di Suriah didominasi oleh kekuatan Islam fundamentalis. Kepada merekalah Washington meletakkan harapannya untuk mengubah wajah baru Suriah pasca Assad kelak. Kenyataan menunjukkan bahwa perilaku kelompok ini dalam perang Suriah bersifat kejam dan brutal, terutama terhadap warga sipil dan tawanan perang di wilayah-wilayah yang mereka duduki. Akibatnya, opini masyarakat dunia telah menempatkan kelompok ini sebagai musuh utama peradaban. Alih-alih mendominasi opini dunia bahwa Assad adalah “biang kerok” di Suriah—sebagaimana yang diharapkan AS dan sekutunya, opini dunia justru menyatakan bahwa persoalan utama di Suriah bukan Assad, melainkan kelompok Islam fundamentalis.
- Perilaku kelompok-kelompok ekstrem bersenjata di Suriah berada di luar bayangan para perancang strategi di Washington. Kelompok-kelompok ini ternyata bukan boneka yang dapat di-setting sesuka hati oleh pembuatnya. Dalam beberapa hal, tindakan mereka tidak saja kerap “keluar” dari skenario awal, tetapi juga telah melampaui batas-batas peri kemanusiaan—sesuatu yang akhirnya juga tidak dapat dibenarkan oleh Washington sendiri. Washington memang tidak sepenuhnya dapat mengendalikan kelompok-kelompok semacam ini. AS gagal memprediksi bahwa perilaku kelompok ini justru menyatukan opini masyarakat dunia bahwa kelompok funamentalis di Suriah merupakan sumber utama persoalan di negeri itu.
- Menghadapi persoalan ini AS dengan terpaksa akhirnya harus memerangi sekutunya sendiri agar terhindar dari tuduhan ikut mensponsori kejahatan perang (war crime) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Akibatnya, rencana strategis yang telah dicanangkan sebelumnya menjadi lumpuh, bukan karena kekuatan militer pemerintah Suriah an sich, melainkan justru karena “dimakan” sendiri oleh AS dan Barat. Peristiwa serangan militer AS dan sekutunya terhadap kelompok-kelompok ekstrem di Suriah telah menjungkirbalikkan secara ironis makna sebuah pepatah lama: “Tuan makan senjata”. Para perencana di Washington agaknya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa mereka akan memerangi sekutunya sendiri di Suriah.
- Namun demikian, serangan militer AS dan sekutunya terhadap kelompok ini lebih tepat dimaknai sebagai upaya “menjewer kuping si anak nakal”, ketimbang melenyapkannya secara permanen. Dalam arti strategis, mereka tetap mitra bagi AS dan sekutunya dengan satu kepentingan dan agenda politik yang sama: mendongkel Assad.
- Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin tertinggi ISIS, sebelumnya adalah tahanan di AS sejak tahun 2004. Pada tahun 2009 ia dilepaskan oleh pemerintah AS karena statusnya dinilai oleh pihak yang berwenang sebagai “Tahanan Tingkat Rendah”. Pasca pelepasannya mustahil kiranya jika intelijen AS tidak melakukan monitoring terhadap al-Baghdadi hingga ia pada akhirnya mendeklarasikan berdirinya ISIS. Hal ini mengindikasikan bahwa AS sekurang-sekurangnya telah mengetahui pergerakan dan rencana-rencana al-Baghdadi. Yang tidak pernah dibayangkan AS adalah perilaku kelompok ISIS yang justru menganggu skenario awal AS di Suriah.
- Klaim kaum fundamentalis bahwa perjuangan mereka berlandasan ideologi (agama) dengan tujuan mendirikan khilafah Islam di Suriah dan Irak memunculkan banyak pertanyaan. Jika perang yang mereka kobarkan bersifat ideologis, mengapa bedil mereka tidak diarahkan pada zionis-Israel? Mengapa operasi militer yang mereka gelar tidak dilakukan di Gaza yang hingga hari ini masih membara karena tekanan militer Israel terhadap warga Palestina? Akibatnya, para analis Timur Tengah—bahkan di Barat sendiri—menarik kesimpulan bahwa kaum fundamentalis yang tengah mengobarkan perang di Suriah juga tidak lepas dari kondisi yang diciptakan Israel. Dengan demikian, kini semakin terkuak secara luas ke publik bahwa proyek penggulingan Presiden Assad tidak saja merupakan bagian dari skenario AS dan Barat (terutama Inggris), tetapi juga melibatkan Israel. Setidaknya Israel dapat berharap bahwa pengganti Assad kelak tidak akan menuntut dikembalikannya dataran tinggi Golan (milik Suriah) yang dicaplok secara tidak sah oleh Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. AS tidak pernah membayangan bahwa skenario rahasia yang dicanangkan bersama sekutunya—yang menggunakan kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menjatuhkan Assad—terbongkar.
- Para perancang strategi di Washington juga luput mempertimbangkan sebuah kemungkinan yang justru dapat merusak skenario awal mereka: hadirnya militer Rusia di kancah perang Suriah. Tindakan militer yang AS dan sekutunya selama setahun lebih untuk menggempur kelompok ekstrem ternyata tidak efektif (karena hanya sekadar “menjewer kuping si anak nakal”) dibandingkan dengan operasi militer Rusia yang hanya membutuhkan waktu lima bulan yang telah berhasil menggiring para ekstremis ke wilayah Alepo—sebagai satu-satunya lokasi di Suriah yang masih berada di tangan mereka.
- Opini dunia menunjukkan bahwa Rusia dinilai jauh lebih sungguh-sungguh dan konsisten dalam membasmi kaum teroris dibanding AS dan sekutunya yang dianggap “setengah-setengah”. Celakanya, para pemimpin AS dan sekutunya berada dalam posisi sulit untuk melawan kuatnya opini semacam ini. Dengan demikian, proxy waryang digelar AS di bumi Syam tidak saja mengalami pukulan telak di medan perang, tetapi juga tak berdaya dalam menghadapi opini publik.
- Kondisi mutakhir peperangan di Suriah kini berada di luar kendali AS dan sekutunya. Rusia, pemerintah Assad, milisi pro pemerintah dan Iran praktis mengendalikan jalannya peperangan. Implementasi skenario AS dan sekutunya, termasuk Israel, mengalami jalan buntu.
Paparan di atas sesungguhnya memperlihatkan problem yang cukup serius di kalangan para pembuat kebijakan di Washington. Dinas rahasia AS, CIA,jelas punya peran penting dalam persoalan ini. Menilik arah dan jalannya peperangan di Suriah tampak bahwa berbagai faktor membuat strategi AS atas negeri itu amburadul. Skenario yang telah direncanakan tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Banyak hal rupanya yang berada di luar perhitungan dan proyeksi CIA—sebagai sebuah dinas rahasia yang menjadi salah satu andalan utama bagi strategi luar negeri AS. Negara adidaya ternyata tidak selamanya digdaya.
Di tengah kondisi semacam itu, yang tersisa bagi AS dan Barat di Suriah hanya memprotes operasi militer Rusia dan mendesak pemberlakuan gencatan senjata. Mereka juga menyerukan agar segera dibuka kembali upaya perundingan antara kaum oposisi dengan pemerintah Suriah. Ini merupakan taktik perang model jadul yang sangat mudah diterka: meminta perundingan karena terdesak secara militer. Sayang, seruan ini hanya sekadar angin bertiup di sisi Putin. Tekad Rusia agaknya telah bulat: melenyapkan para teroris dari peta geopolitik Suriah.
Jika oposisi dapat dilenyapkan, maka skenario AS dan Barat untuk membawa persoalan Suriah ke meja perundingan dalam rangka mengupayakan transisi dan suksesi kepemimpinan di negeri ini (baca: mencopot Assad dari kursi kepresidenan), tentu saja akan menjadi sia-sia belaka. Efektifitas operasi militer Rusia dalam mempersempit dan melemahkan kekuatan kaum oposisi Suriah, dengan demikian, akan menghilangkan alasan bagi AS dan Barat yang menuntut perundingan dengan mengikutsertakan kaum oposisi. Pertanyaannya adalah, jika oposisi lenyap dari bumi Suriah, dengan siapa Assad harus berunding?
Penulis: Rahadi T. Wiratama, Peneliti LP3ES, Redaktur Prisma, Direktur Kalimasadha Nusantara Institute dan Associate Researcher GFI.