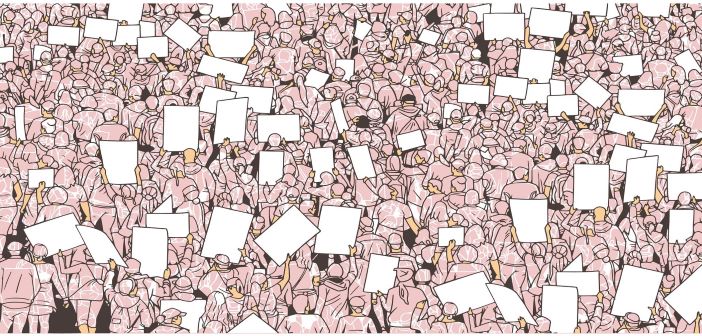Pokok-Pokok Pikiran Geopolitik
Pasca Orde Baru jatuh, Indonesia terjebak dalam sistem politik yang cenderung serta berorientasi pada kapitalis liberal, terutama usai UUD 1945 diamandemen empat kali pada kurun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Berbasis konstitusi (hasil amandemen), era tersebut membidani apa yang disebut dengan istilah ‘demokrasi glamor’. Begitu kira-kira ringkasnya.
Apa demokrasi glamor itu?
Ya, selain tata cara demokrasi yang abai terhadap local wisdom leluhur (musyawarah mufakat) alias meminggirkan hak bicara, terlalu gaduh, meniru model demokrasi ala Barat (hak suara), tampak gemerlap di atas permukaan tetapi miskin substansi, dan rata-rata kegaduhan yang ditimbulkan tidak menyentuh kepentingan nasional. Juga, paling menyedihkan dalam demokrasi glamor ialah pembelahan terhadap rakyat. Sekali lagi, “Model demokrasi kini justru membelah rakyat”. Itu yang utama. Dan inilah poin urgen lagi sangat-sangat memprihatinkan. Namun sungguh unik, tak sedikit para elit politik serta mayoritas rakyat sendiri malah menikmati keterbelahan sosial tersebut. Entah kenapa.
Pertanyaan selidik, “Apakah para elit dan perumus kebijakan di republik ini tidak menyadari kondisi keterbelahan yang kini terjadi, “tutup mata” alias mereka tahu tetapi pura-pura tidak tahu karena turut menikmati keterbelahan?”
Adapun anatomi inti serta penyebab demokrasi glamor dapat di-breakdown sebagai berikut: 1) one man one vote; 2) multi partai: 3) otonomi daerah, dan seterusnya. Memang unik. Ketiga poin di atas justru merupakan amanat UU pada satu pihak, namun di pihak lain dianggap sebagai bahan bakar kegaduhan serta sarana pembelah rakyat.
Ada senyap adu domba melalui konstitusi, atau devide et impera terselip dalam sistem politik kita. Canggih. Demokrasi dijadikan alat pembelah serta modus adu domba antarsesama anak bangsa. Sekali lagi, inilah yang kini berlangsung secara sistematis, masive, bahkan terstruktur dan berkala setiap lima tahunan (pemilu).
Tak dapat dipungkiri, bahwa proses pembelahan warga tersebut berjalan dalam skala nasional, terutama saat digelar hajatan pemilihan presiden (pilpres), seketika warga terpecah. Pro ini, pro itu. Ini terjadi hingga ke dapur-dapur rumah tangga. Sepasang suami istri misalnya, atau perkawanan yang berjalan lama, bisa renggang hanya gegara beda pilihan. Ini fakta politik serta realitas sosial.
Tak bisa dibantah, bahwa stigma Kecebong dan Kadrun pun lahir dari rahim demokrasi ini. Dan sepertinya, ia dipermanenkan oleh invisible hand.
Kegaduhan tersebut katanya atas nama kedaulatan rakyat. Tetapi, sebagian rakyat kurang memahami bahwa dampak demokrasi semacam ini, kedaulatan rakyat hanya sebatas di bilik-bilik TPS. Sebab, usai pencoblosaan, kedaulatan pun berpindah —dibajak— ke/oleh partai politik (parpol). Jangankan berdaulat, bahkan untuk menitip aspirasi pun sudah tak ada lagi saluran akibat kuatnya peran ketua parpol. Gilirannya, medsos pun jadi ‘medan tempur’-nya.
Klimaksnya ialah, tatkala sistem MPR diubah dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi selevel DPR, BPK, MK dan lain-lain. Hal ini berdampak, selain Presiden tidak lagi sebagai Mandataris MPR, GBHN pun tak ada lagi. Lenyap. Selain Presiden cenderung menjalankan politik bukan GBHN, juga hampir semua ditentukan oleh parpol pada satu sisi, sedang parpol cenderung bersandar kepada kaum pemodal di sisi lain. Gilirannya, arah kebijakan negeri ini tidak lagi ditentukan GBHN, tetapi berbasis kepentingan oligarki politik dan oligarki ekonomi.
Singkat kata, bahwa kegaduhan di era pasca Orde Baru, sebenarnya diciptakan oleh sistem politik hasil empat kali amandemen UUD 1945 dimana tahapannya, menurut Pak Try Soetrisno, Wapres RI ke-6, tidak berjalan ideal karena kuatnya pengaruh asing. Itulah bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945, ujar Pak Try.
Pe-er bagi segenap anak bangsa ialah, “Bagaimana menghentikan praktik demokrasi glamor yang mahal, miskin substansi, dan justru memangkas kedaulatan rakyat?”
Sebenarnya mudah, tetapi gampang – gampang susah. Gampang di teori, susah dalam praktik. Kenapa? Sebab, para oligarki politik dan oligarki ekonomi tak akan rela serta tidak bakal berpangku tangan. Mereka terlanjur nyaman dalam kondisi ini.
Sesuai pertanyaan di atas, tahapan yang direkomendasikan ialah sebagai berikut:
Pertama, kembalikan sistem politik atau konstitusi kita sesuai Naskah Asli UUD yang lahir pada 18 Agustus 1945;
Kedua, hal-hal yang dianggap baik dari hasil amandemen empat kali UUD tetap dipertahankan, tetapi ditempatkan dalam adendum. Jadi, teks asli tetap utuh;
Ketiga, eksekusi di tataran operasional nantinya, langsung saja menukik kepada ‘bahan bakar dan sumber kegaduhan’, misalnya, kembalikan local wisdom hak bicara (musyawarah mufakat) menggantikan one man one vote (hak suara); fusikan multi partai menjadi dua/tiga partai; ubah otonomi daerah yang membidani raja-raja kecil di daerah menjadi sentralisasi kekuasaan.
Pada masa transisi kelak, (mungkin) bisa ditiru model sistem politik di Rusia, dimana para kepala daerah setingkat Gubernur ditunjuk oleh Presiden kecuali Bupati/Walikota. Mengapa? Gubernur hanya perpanjangan tangan pusat. Ia tak punya wilayah kecuali daerah khusus dan/atau daerah istimewa.
Demikianlah pokok-pokok pikiran geopolitik disajikan secara singkat. Tidak ada maksud menggurui siapapun, terutama para pihak yang berkompeten. Sekedar diskusi serta sharing konsepsi demi kejayaan bangsa dan negara.
Demikian adanya.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
Facebook Comments