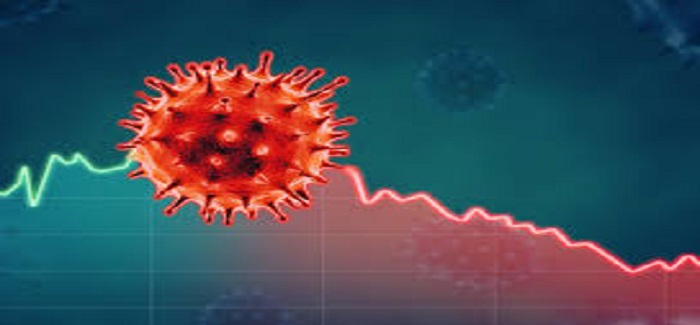Tulisan ini secara khusus akan memotret dampak terhadap masa depan ekonomi dan geopolitik internasional. Sebagaimana dalam pandangan penulis bahwa pelemahan terhadap perekonomian nasional nasional, baik itu sebagian atau seluruhnya dipicu melalui penegakan pada apa yang disebut “pedoman WHO” yang berkaitan dengan lockdown (penguncian), pembatasan perdagangan dan transportasi, dan lain-lain.
Lembaga-lembaga keuangan yang kuat dan kelompok-kelompok lobi termasuk Wall Street, Big Pharma, World Economic Forum (WEF) dan Yayasan Bill dan Melinda Gates terlibat dalam membentuk “pedoman WHO” terkait pandemi COVID-19.
Lockdown (penguncian) bersama dengan pembatasan perdagangan dan perjalanan udara telah mengendalikan keseluruhan ‘isi cerita’ di atas panggung. Penutupan ekonomi nasional ini dilakukan di seluruh dunia mulai bulan Maret, yang secara simultan mempengaruhi sejumlah besar negara di semua wilayah utama dunia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Dunia.
Operasi penutupan ini mempengaruhi jalur produksi dan pasokan barang dan jasa, kegiatan investasi, ekspor dan impor, perdagangan grosir dan eceran, pengeluaran konsumen, penutupan sekolah, perguruan tinggi dan universitas, lembaga penelitian, dan lain-lain.

Pada gilirannya semua ini menyebabkan pengangguran massal, kebangkrutan perusahaan kecil dan menengah, kehancuran daya beli masyarakat, meluasnya kemiskinan dan kelaparan di pelbagai negara.
Perlu juga penulis sampiakan di sini bahwa di seluruh dunia, ekonomi nasional hanya selamat dari rezim Bretton Woods selama mampu mempertahankan kontrol terhadap mata uang mereka. Elemen utama dalam perang ekonomi yang dilakukan oleh Kekaisaran AS sejak 1945 adalah menghapuskan nilai tukar tetap. Setelah mencurangi rezim moneter internasional pascaperang untuk menggantikan mata uangpound Inggris dengan dolar AS sebagai mata uang patokan, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) dikerahkan untuk menstabilkan dolar AS dengan keuntungan atas mata uang Eropa lama.
Meskipun secara resmi ini adalah lembaga internasional, namun raksasa monoter internasional tersebut diorganisasikan seperti perusahaan swasta. Keputusan harus dibuat oleh mayoritas saham yang disimpan di IMF atau Bank Dunia. Karena AS memegang mayoritas modal di keduanya, AS seolah aktor utama yang mengendalikan suara terbanyak atas keputusan Dana atau Bank.
Mata uang semu Dana dan Bank disebut hak penarikan khusus (SDR). Unit-unit akun ini didasarkan pada nilai tertimbang mata uang “cadangan” yang mendasarinya, terutama USD. SDR ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perbedaan neraca pembayaran. Anggota IMF diperpanjang SDR sesuai dengan kekuatan relatif ekonomi mereka. Berdasarkan SDR yang dialokasikan untuk suatu negara, ia dapat menarik dolar atau mata uang cadangan lain dalam jumlah yang cukup untuk membayar ketidakseimbangan sementara antara impor dan ekspor, transaksi-transaksi yang setelah Perang Dunia II hampir semuanya merupakan bisnis dalam kendali USD.
Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Jamaika Michael Manley – ketika perjanjian Bretton Woods ditandatangani sebagian besar negara, seperti Jamaika, masih merupakan koloni atau protektorat dari kekuatan Eropa atau Amerika Utara. Karenanya tidak ada ketentuan yang dibuat bagi mereka untuk memiliki ekonomi independen atau mata uang nasional.
Akibatnya sebagian besar populasi dunia dan negara-negara baru yang merdeka yang tidak mengadopsi versi mata uang Euro-Amerika tidak memiliki cara untuk memonetisasi aktivitas ekonomi mereka dalam perdagangan internasional. Mereka dibiarkan sepenuhnya bergantung pada USD, GBP, dan untuk perdagangan luar negeri dalam bentuk apa pun.
Untuk membatasi hegemoni USD di Afrika, Prancis menciptakan CFA- Franc. Franc Afrika ini mengikat bekas-bekas jajahan Afrika-nya ke Prancis dengan memberikan nilai tukar yang menguntungkan kepada Franc-CFA dengan Franc Prancis, meskipun tidak setara. Namun secara keseluruhan, gerakan kemerdekaan pascaperang semua dihadapkan dengan ketergantungan yang melekat pada sistem mata uang mereka dari intrik bank-bank AS dan Eropa dengan mengendalikan dua pasar valuta asing utama, the City dan Wall Street. Pengecualian untuk rezim ini adalah Uni Soviet dan COMECON pada dan setelah Kuba 1959.
Ketika ekonomi AS menghadapi kemungkinan keruntuhan finansial menjelang akhir perangnya di Vietnam (AS telah berhasil mentransfer biaya Perang Korea ke “Perserikatan Bangsa-Bangsa”), negosiasi rahasia oleh pemerintah Nixon dengan Kerajaan Arab Saudi pun dilakukan di kantor mereka dalam OPEC, untuk menghemat USD dengan menghapuskan penetapan emas dan menetapkan USD sebagai satu-satunya mata uang untuk perdagangan minyak dunia.
Maka, negara mana pun yang tidak memiliki pasokan minyak domestik atau harus memperdagangkan minyak di pasar dunia terpaksa menggunakan dolar AS. Untuk membuktikan hal tersebut, rezim AS tidak pernah ragu-ragu untuk berperang melawan anggota OPEC yang tidak mematuhi aturan besi ini. Tentu saja AS adalah satu-satunya negara yang dapat mengeluarkan dolar AS dan bank-banknya adalah mereka yang dapat menjual utang dalam mata uang USD, secara langsung atau tidak langsung, karenanya peran sentral Sistem Federal Reserve – kartel perbankan swasta yang disewa untuk mengeluarkan uang tunai dan mengendalikan kebijakan moneter AS.
Rezim AS juga telah menempuh kebijakan yang ketat untuk menarik semua dolar kembali ke aset AS atau mengizinkan entitas AS memperoleh aset asing sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan USD dan menghasilkan uang bisnis swasta (sementara di sisi lain melarang monetisasi utang publik untuk layanan sosial, infrastruktur, dll.)
Konteks di mana perang ekonomi saat ini terjadi antara AS dan Cina dan pada tingkat lebih rendah antara AS dan Rusia patut dicermati oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah di seluruh dunia. Perang ekonomi ini memasuki fase baru dengan serangan Wuhan.
Bertolak dari serangan Wuhan pula, otoritas Eropa dan AS memerintahkan berbagai tingkat penguncian (lockdown) dan perjalanan internasional, bahkan di dalam UE sendiri, terhenti secara virtual. Maskapai, hotel, dan sektor perjalanan lainnya praktis tidak beroperasi sebagaimana biasanya. Sektor transportasi juga sangat terbatas. Ekonomi sehari-hari kian sulit akibat kebijakan lockdown tersebut.
Apa manfaat dari lockdown di Barat ini? Penulis mencermati bahwa virus korona begitu mengejutkan perekonomian secara keseluruhan di banyak negara. Apakah kita harus percaya bahwa itu hanya pengawasan dari pihak pemerintah untuk merenungkan kontingensi terhadap epidemi tetapi tidak untuk ekonomi? Namun, apa yang benar-benar sangat penting mereka yang punya kendali atas pemerintahannya adalah uang dan tentu saja kekuatan yang menyertainya.

Adapun konsekuensi langsung dari penguncian (lockdown) dalam hal ekonomi, diantaranya adalah:
1. Adanya pembatasan perjalanan terhadap mereka yang umumnya aktif dan punya mobilitas tinggi (setidaknya di UE)
2. Adanya pembatasan yang berpotensi melumpuhkan sektor UKM secara signifikan
3. Adanya obstruksi transaksi rantai pasokan, tidak terkecuali dengan Cina
4. Adanya peningkatan pengangguran yang sangat signifikan
5. Kenaikan harga yang tak terelakkan, apakah kelangkaan diinduksi atau karena tambahan biaya “keamanan”
6. Terciptanya potensi lapisan korupsi dan lalu lintas selundupan yang tidak hanya akan menaikkan harga kehidupan sehari-hari tetapi juga mengkriminalkannya.
Pada saat yang sama kami telah mendengar lebih dari beberapa laporan tentang Quantitative Easing (QE) baru alias memberikan triliunan kepada bank.
Quantitative Easing merupakan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar guna meningkatkan perekonomian dengan cara membeli aset-aset jangka panjang berupa surat-surat berharga pemerintah maupun bank komersial. Kebijakan moneter ini diambil untuk menciptakan inflasi sehingga mampu mencegah risiko deflasi.
Pada kebijakan moneter Quantitative Easing, bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar di pasar dan mendorong bank-bank komersial agar bersedia menggelontorkan pinjaman atau kredit baik usaha maupun konsumtif kepada perusahaan dan juga masyarakat.
Kebijakan Quantitative Easing itu diambil karena adanya potensi kelesuan dan krisis ekonomi. Di saat perekonomian krisis, bisnis di beberapa sektor lesu, angka pengangguran tinggi, tingkat permintaan rendah, dan pastinya tingkat pendapatan masyarakat rendah. Dengan kebijakan Quantitative Easing, jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga jangka pendek pada level mendekati 0%. Tujuannya, masyarakat bahkan perusahaan terdorong untuk mengajukan pinjaman jangka pendek dengan bunga rendah tersebut.
Pemberian pinjaman kepada perusahaan dan masyarakat tersebut ‘diharapkan’ mampu mendorong tingkat pengeluaran atau konsumsi yang tinggi. Jika hal ini terjadi, artinya tingkat permintaan atau belanja masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan juga semakin tinggi. Adanya permintaan yang tinggi, kegiatan produksi kembali dipacu agar mampu memenuhi permintaan tersebut.
Dengan demikian, perekonomian mulai menggeliat dan melaju menuju stabilitas yang diharapkan. Namun persoalannya, tidak semua negara-negara di dunia yang berhasil mengambil kebijakan Quantitative Easing, bahkan justru malah menyeret negara tersebut ke jurang utang yang lebih dalam.
Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Institute