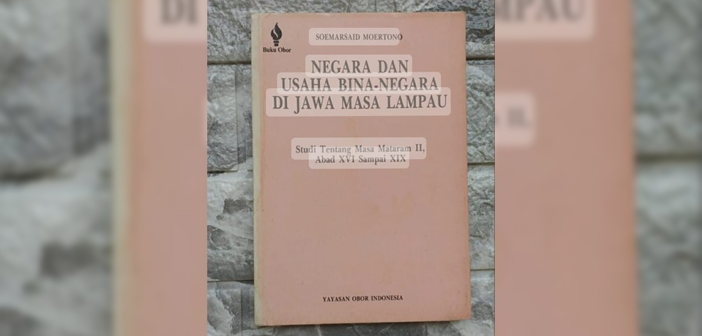Resensi oleh: Onghokham
Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Studi Tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985.
Akhirnya karya Soemarsaid Moertono terbit dalam bahasa Indonesia. Studi mengenai kerajaan Mataram ini telah diterbitkan pada tahun 1968 dalam bahasa Inggris sebagai seri monografi Cornell University Modern Indonesia Project. Studi ini merupakan tesis MA dalam ilmu politik pada Cornell University. Biarpun karya ini termasuk ini termasuk tesis MA sebenarnya ia sejajar dengan tesis Ph.D, dan dalam banyak hal mungkin melebihi tesis Ph.D yang kurang bermutu. Dengan singkat studi Moertono merupakan suatu karya klasik mengenai kerajaan Jawa agraris. Buktinya, monograf-nya dalam bahasa Inggris sudah mengalami cetakan kedua, yakni pada tahun 1981. Jarang sekali suatu monograf mengalami cetakan kedua dan bahwa studi Soemarsaid dicetak ualng membuktikan sifat klasiknya studi tersebut.
Sebelum membicarakan lebih lanjut studi Moertono ini, saya ingin memberi sedikit mengomentari mengenai terjemahannya, khususnya terjemahan judul buku. Judul buku aslinya adalah State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period . . . , dan ini diterjemahkan sebagai Negara dan Usaha Bina Negara . . . Menurut pendapat kami terjemahan Statecraft sebagai Usaha Bina Negara adalah kurang tepat karena kurang memperlihatkan sifat Machiavellisme (kebijaksanaan real tanpa kasihan) yang menjadi ciri dari politik Mataram. Mungkin istilah Negara dan Tipu-Muslihat Negara atau Negara dan Politik-Real-Negara adalah lebih tepat. Tipu-Muslihat atau Politik-Real juga lebih tepat dengan istilah Statecraft. Selain itu dengan dipakainya judul Bina-Negara terlalu banyak tekanan diberikan pada istilah Negara sedangkan dari studi ini jelas bahwa statecrafts berasal dan di tangan sang raja, bukan di tangan negara sebagai lembaga atau golongan elite (kekuatan sosial). Dengan singkat dalam studi Moertono, Raja adalah negara dan statecraft berada di tangan satu-satunya penguasa tertinggi ini yang bergelar “pusat” Buwana (Hamengku . . . atau Paku . . .), Panglima Perang (Senapati Ingalaga) Sjeick Sahidin Panatagama (Orang yang paling suci, Pengatur Agama).
Studi Moertono ini merupakan satu model kerajaan Jawa agraris dengan contoh yang diambil adalah Mataram ke-II. Terjemahan Old Java sebagai “Masa Lampau” juga kurang tepat sebab Moertono membicarakan “Jawa Tradisional” atau Jawa yang Lama/kuno. Studi ini terutama menekankan aspek ideologis dari Statecraft. Jadi konsep mengenai posisi raja, raja yang wicaksana itu bagaimana, hubungan raja dengan para priyayinya, hubungan raja dan rakyat dari segi ideologis. Namun buku ini kurang mempersoalkan masalah-masalah ekonomi, perang, pengawasan, dinas mata-mata, dan segi-segi konkrit lain dari statecraft sang raja. Dari penjelasan mengenai konsep ideologis ini sangat jelas muncul struktur masyarakat dan kerajaan Mataram ke-II. Kerajaan mana adalah, khususnya untuk Jawa Tengah, tradisi monarkis yang terakhir dan konsep kenegaraan Raja yang masih hidup di sebagian penduduk Jawa. Banyak sekali prinsip-prinsip dari kerajaan Mataram lama ini yang masih digunakan kini seperti manunggaling kawula-lan-gusti (menyatunya raja dan rakyat), tut wuri ing andayani (momong dari belakang) dan sebagainya.
Sebaliknya hubungan sosial-ekonomi masyarakat kita kini tentu sudah jauh berbeda dari Mataram II. Apakah hal ini cukup disadari oleh semua pihak yang bersangkutan? Pertama-tama bagaimana situasi-kondisi kerajaan Mataram ini. Mataram atau Jawa pada zaman jayanya Mataram (abad 16-18) memiliki jumlah penduduk yang relatif sangat sedikit hampir seperti Kalimantan kini bila dibandingkan dengan jumlah tanah yang ada. Ini berarti orang dapat selalu melarikan diri dari pemerintahan atau dari Mataram. Hal ini terjadi dalam batas-batas tertentu. Namun seperti seorang ahli politik Asia Tenggara, James C. Scott dari Yale University mengatakan, rakyat Asia memberikan suara mereka dengan “kaki”, artinya berdiam dengan yang berkuasa atau lari darinya. Lari dalam arti konkrit, meninggalkan wilayah dari yang dipertuan, dan Tuan tanpa pengikut adalah yang dipertuan tanpa kekuasaan sebab jumlah orang yang dibawahinya, yang taat padanya selalu menjadi ukuran ekonomi (pajak), militer dan politis.
Unsur kedua mengenai Mataram ini adalah bahwa pemerintahan berarti sedikit sekali bagi masyarakat. Mataram tidak mau serta sadar tidak dapat mengatur semua. Tanah yang luas dan langkanya penduduk serta terbatas dan primitifnya alat pemerintahan menciptakan kekosongan kekuasaan. Lalu timbul obsesi Mataram menguasai masyarakat, sebaliknya orang dengan mudah mengelakkan diri dari penguasaan ini.
Moertono selanjutnya sangat menekankan aspek ideologis dan susunan kerajaan Mataram. Pada zaman tersebut orang belum mengenal ilmu pemerintahan atau ilmu lain. Orang mendekati masalah dunia melalui agama, mythos, perwayangan dan kebudayaan pada waktu itu. Dunia menurut konsep tradisional ini adalah hanya suatu refleksi dari makrokosmos atau alam semesta (agama). Kerajaan harus disusun dan dilegitimir sebagai suatu mikrokosmos yang merupakan cermin dari makrokosmos. Jadi kalau ada satu Tuhan, maka di dunia pun hanya ada satu Raja yang berkuasa mutlak dan berdiri pada kedudukan yang paling atas. Berbagai istilah untuk raja seperti Pangeran atau Gusti dipakai juga untuk Tuhan. Raja sendiri bergelar Paku atau Hamengku (pusat) Buwana, Senapati Ingalaga (Panglima Perang), Sjeich Sahidin Panatagama (Orang Suci, Pengatur Agama). Sebelumnya ada gelar lain seperti Susuhunan (Yang dijunjung, Yang didukung), atau Sultan yang menunjukkan bahwa raja Mataram setingkat dengan Sultan Otoman, kerajaan Islam terbesar pada waktu itu. Raja Mataram pertama bergelar Panembahan (yang disembah rakyat).
Kalau hubungan antara Raja dan Rakyat (kawula) adalah menurut konsep Islam Sufi yang menekankan pada bersatunya (manunggaling Kawula-dan-Gusti) yang berarti tunduknya rakyat pada pada kehendak raja maka simbol-simbol lain datang dari konsep Deva-Raja. Tahta raja disebut Siti-Inggil, tanah yang dinaikkan, yang lebih tinggi dari sekitarnya atau mengungkapkan gunung. Menurut mitologi Hindu di Asia Tenggara, para dewa tinggal di atas gunung (mahameru/Semeru). Konsep ini dilambangkan dalam istilah untuk tahta, dan arsitektur kraton sebab para dewa di dunia (raja, priyayi dan penghuni istana yang lain) juga harus tinggal di atas gunung yang simbolis (Siti-Inggil). Atap bangunan kraton misalnya, mirip gunung. Dihampir semua kota kraton terdapat tugu dan pun di ibukota Republik Indonesia, Jakarta, terdapat Monas, yakni bangunan tugu. Tugu melambangkan gunung dan lingga simbol kesuburan dan kemakmuran. Pentingnya konsep gunung ini dalam kerajaan Indonesia sudah terlihat pada nama dinasti Crivijaya, yakni Cailendra, Yang dipertuan di Gunung. Khususnya gunung Lawu sangat penting dalam pusaka kraton Mataram, sepenting Nyai Loro Kidul. Namun juga gunung-gunung lain seperti Merapi, Sindoro, Sumbing adalah penting.
Bila orang menerima beberapa asumsi pokok mengenai ideologi kerajaan Mataram ini, maka seluruh susunan dan pemikiran mengenainya adalah suatu kesatuan logis. Hal ini menunjukkan bahwa orang Jawa pada waktu itu dapat berpikir logis, namun harus dapat menerima asumsi-asumsi yang berakar pada kebudayaannya dan sering tidak menurut ukuran kebenaran obyektif.
Pun pada zaman Mataram rupanya tidak semua orang selalu setuju dengan asumsi-asumsi pokok yang berasal dari konsep deva-raja ini sebab raja tetap harus mempergunakan perang, teror, menindas pemberontakan dan lain-lain. Dinasti-dinasti dan pemerintahan raja tidak selalu stabil. Bahkan sangat tidak stabil. Moertono mungkin kurang memperhitungkan pengaruh kehadiran VOC/Belanda dalam memperkuat kedudukan raja, sebab sebelumnya kedudukan mereka masih harus dibagi dengan para darah dalem atau keluarga. Baru dengan stabilisasi dari VOC kedudukan raja menjadi lebih mutlak. Walaupun begitu ia sering tidak memiliki cukup alat kekuasaan untuk merealisirnya.
Biarpun saya lontarkan kritik buku Moertono ini tetap merupakan satu karya klasik dan sangat menambah khasanah pengetahuan kita mengenai konsep tradisionil dan kebudayaan jawa. Siapa saja yang memiliki perhatian pada kebudayaan Jawa patut membacanya. Sudah tentu orang Jawa sendiri.
Sumber: Prisma No 5, Mei 1986