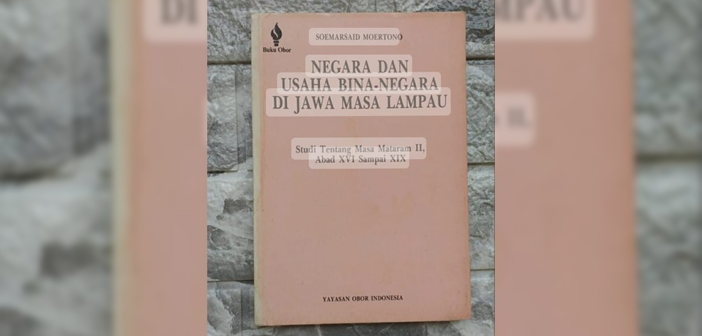Resensi oleh: Haryo Kunto Wibisono
Tentang buku State and statecraft in old Java : a study of the later Mataram period, 16th to 19th Century (1)
Buku terkenal karya Soemarsaid Moertono ini diterjemahkan pertama kali tahun 1985, kemudian terbit lagi terjemahannya lagi tahun 2017. Menariknya, masing-masing membuat judul terjemahan yang agak berbeda. Pada terjemahan pertama kali mendapatkan tinjauan oleh sejarawan, sedang terjemahan mutakhir diresensi kandidat doktor antropologi.
Ketika penulisnya wafat, tahun 1987, ada dua tulisan, dari Umar Kayam dan Taufik Abdullah yang menyinggung buku ini juga. Namun majalah Tempo yang memuat tulisan tersebut entah terselip di mana.
Judul buku: Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX
Penulis: Soemarsaid Moertono
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Cetakan: I, 2017
Tebal: xxv + 249 halaman
ISBN: 978-602-424-678-5
Saat layar tahun 2018 dibuka, seluruh khalayak di Indonesia merayakannya sebagai tahun politik. Semua mata memandang Jawa yang dianggap patokan bagaimana memenangkan pertarungan politik di seantero Republik Indonesia. Dalam peristiwa politik, pulau yang diposisikan sebagai pusat pemerintahan, episentrum kegiatan politik, pertumbuhan ekonomi, dan konsentrasi penduduk ini memunculkan istilah terkenal, yaitu Jawa adalah kunci.
Persoalannya, bagaimana konsep kuasa dan praktik bernegara dalam alam pikiran Jawa? Di sinilah buku berjudul Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX karya Soemarsaid Moertono hadir memberikan jawaban.
Buku ini membahas dua poin. Pertama, kedudukan raja pada masa Mataram II (abad ke-16 samapai abad ke-19). Kedua, bagaimana kekuasaan diterapkan pada soal-soal praktis dan alat apa saja yang dimiliki raja untuk mencapai tujuannya. Lembaga negara yang diberlakukan sebagai pusat dan penguasa atas segalanya memberikan tanda tanya besar bagi Moertono, bagaimana cara raja membenarkan kedudukannya dan membuatnya supaya diterima. Moertono menjawab pertanyaan ini melalui sumber sejarah yang terbentang dari Pakem Pewayangan, Sastra Babas, Piwulang, hingga angger (peraturan) dan piagem (piagam).
Hierarki Patronase
Moertono menunjukkan bahwa urat nadi kekuasaan raja-raja Jawa disusun oleh hierarki kawulo-gusti. Kawulo terdiri dari para hamba, wong cilik, dan rakyat kebanyakan, sedangkan gusti meliputi tuan, birokrat kerajaan, atasan, dan penggedhe. Hierarki ini menekankan keseimbangan, harmonisasi, serta ketegasan pembagian peran dalam masyarakat, hak dan kewajiban, status sosial, pakaian, hingga cara berbicara yang sudah ditentukan “dari sananya”.
Keseimbangan ini ditopang keyakinan akan nasib/ketentuan (pinesti) dan takdir (tinitah). Hasrat akan hadirnya harmonisasi ini diilhami oleh keyakinan kosmologis masyarakat Jawa. Sistem ini mengamini segala sesuatu sudah diatur oleh alam semesta dan apa pun yang terjadi hanya pergantian musim. Pemahaman ini menjelaskan mengapa di negara agraris tiap gangguan, seperti pemberontakan, dianggap menggoyang keseimbangan alam. Masyarakat dan negara diasumsikan sebagai ikatan yang melekat satu sama lain dan akrab selayaknya keluarga. Namun, dalam ikatan ini campur tangan negara dalam keseharian masyarakat dinihilkan dan kekuasaan diarahkan pada merawat ketaatan aturan sosial. Selanjutnya, dalam rangka memelihara keseimbangan sangat diharuskan komunikasi berbentuk pralambang dan pasemon yang lebih kurang berarti informasi terselubung. Kemunikasi ini sangat menghindari penggunaan bahasa kasar dan keterusterangan sebab peringatan kasar hanyalah untuk orang rendahan (hlm 29).
Napas keseimbangan dalam relasi negara-masyarakat ini berangkat dari keyakinan akan dua elemen, yaitu mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos tempat berlangsungnya interaksi manusia, sementara makrokosmos ranah supra-manusia. Raja dan negara—sebagai pimpinan ruang mikrokosmos—diletakkan sebagai replika atas kekuasaan Tuhan. praktik ini terwujud dalam pengandaian raja sebagai pimpinan keagamaan (panatagama) atau wali Tuhan (kalipatullah).
Kultus Kemegahan
Moertono mengamati para raja cenderung menampilkan kepemilikan sarana material (kelimpahan harta) dan keunggulan spiritual (kesempurnaan batin). Ia menyebutnya sebagai Kultus Kemegahan dengna tujuan bukan sekadar untuk memamerkan betapa berkuasanya sang raja, tapi simbol kemakmuran negara. Kultus ini dihasilkan pula melalui sakralisasi perangkat kekuasaan mulai dari sarana spiritual , silsilah raja (leluhur), persekutuan raja dengan alam gaib, harta benda, dan pusaka. Segala perangkat kekuasaan ini, menurut Moertono, bisa dijelaskan dengan pemahaman kosmologi Jawa yang mengartikan raja sebagai wujud pemerintahan Tuhan dan bertujuan untuk mempertahankan keselarasan dan ketertiban dalam dunia manusia (hlm 104).
Buku ini juga mencatat bagaimana raja menafsir wilayah kedaulatan. Melalui cara pandang model konsentrik, maka kekuasaan dibayangkan seperti lingkaran yang berpendar keluar. Semakin jauh maka semakin pudar, sebaliknya jika semakin dekat maka kuatlah pengaruhnya. Logika kedaulatan wilayah ini tergambar pada tiga klasifikasi, yaitu nagara (ibukota), nagaragung (negara inti), mancanagara (daerah pesisir dan termasuk daerah luar), kemudian tanah sabrang (tanah di seberang laut). Metafora ini tergambar pula dalam ucapan dalang pewayangan yang menyatakan negara telah mencapai kemasyhurannya sampai jauh ke mana-mana dan merupakan dunia yang terang benderang. Jadi negara diibaratkan sebagai obor yang terang dan memancarkan sinarnya ke luar (hlm 161).
Di bagian pengantar, sejarawan Peter Carey menuturkan, seorang indonesianis terkemuka, Benedict Anderson, mengaku sangat terpengaruh buku ini saat menulis artikel The Idea of Power in Javanese Culture (1972). Ide tentang kekuasaan Jawa bagi Om Ben—sebutan akrab Benedict Anderson—dianggap sangat konkret, menyeluruh, dan termanifestasikan mulai dari alam semesta, benda bertuah, roh, metafora, serta hubungan antarmanusia itu sendiri.
Kritik buku ini adalah kecenderungan untuk melihat negara sebagai pemain utama dalam konfigurasi kekuasaan. Buku ini tidak mengulas secara mendalam dinamika antara aktor negara (birokrasi kerajaan) yang berkuasa secara legal dan formal saat berurusan dengan otoritas informal dalam pembentukan formasi negara Jawa. Antropolog Joshua Barker (2009) menunjukkan peran otoritas informal seperti preman, jago, dan jawara sebagai aktor yang menentukan rupa kekuasaan negara di level masyarakat. Justru mereka dianggap dan berlaku seperti raja di kalangan masyarakat, uniknya para kelompok ini berkuasa karena faktor wibawa, karisma, dan kesaktian sebagaimana otoritas negara formal.
Terlepas dari kritik di atas, Moertono sebagai sejarawan memberikan refleksi historis atas problem kepemimpinan, etika politik, bagaimana menjalankan kekuasaan, dan relasi negara-masyarakat, yang merupakan topik hangat dalam proses demokratisasi dan bernegara di Indonesia. Buku ini berkontribusi pada perdebatan tentang negara, yang tidak melulu dilihat sebagai lembaga kaku pemberi garis demarkasi antara negara dan masyarakat. Sebaliknya, negara bisa menyebar kekuasaanya melalui metafora, wacana, perkataan, atau praktik sehari-hari.
*) Haryo Kunto Wibisono, Mahasiswa Doktor Antropologi Universitas Indonesia
Sumber: Kompas, 21 Maret 2018