Sesi Belajar Geopolitik
Kendati kolonialisme fisik di Indonesia telah selesai pada 17 Agustus 1945, tetapi secara nonfisik (penjajahan) belum usai. Bahwa kolonialisme masih berlanjut hingga kini namun dalam “wajah” berbeda. Lebih soft, tetapi kerusakan yang ditimbulkan tak kalah dahsyat dibanding penjajahan fisik/klasik.
Wajah lain kolonialisne (nonfisik) itu antara lain berupa penjajahan pikiran, misalnya, atau kolonialisme mental, budaya dan seterusnya. Yang paling dahsyat justru kolonialisme sistem karena dampaknya multi efek.
Apakah kolonialisme sistem itu?
Ia semacam modus penjajahan yang ditanam pada konstitusi atau sistem politik di sebuah negara meski negeri itu sudah merdeka. Dengan kata lain, si penjajah belum legowo melepas wilayah koloninya. Selanjutnya untuk mengontrol secara diam-diam ia tanam sebuah muslihat atau trik di negara yang hendak dilepas. Itu penjelasan singkatnya soal penjajahan sistem.
Nah, catatan ini hanya mengingatkan dan sifatnya menerangkan tentang suatu model devide et impera yang ditanamkan pada (sistem) konstitusi terutama tatkala euphoria reformasi 1998 dibajak oleh asing lewat amandemen 4 kali UUD 1945. Gilirannya UUD 1945 sekarang dijuluki “UUD 2002”, bahkan ada yang menyebut sebagai UUD Palsu.

Uniknya, sebagian anak bangsa hampir tidak sadar diri bahkan kerap larut dalam agenda yang diremot (kepentingan) asing via UUD 2002.
Lantas, bagaimana corak dan modus kolonialisme sistem?
Banyak lagi beragam. Terutama modus melalui UU dan berbagai kebijakan yang dibidani oleh UUD hasil amandemen. Satu contoh saja, misalnya, one man one vote (satu orang satu suara), ini model adu domba yang terus berlangsung secara senyap di Bumi Pertiwi namun bangsa ini asyik mengunyahnya atas nama demokrasi, sedang “kerusakan” negeri terus terjadi akibat modus ini.
Mana bukti kerusakannya?
Ketika berlangsung hajatan politik entah pilpres, pilkada, ataupun pilkades, nah — seketika para warga/rakyat langsung tersegregasi secara politis. Rakyat terbelah saling berhadapan antara satu dan lainnya. “Pro ini, pro itu”. Dan itu pula yang melahirkan para buzzer dengan berbagai motif. Ada buzzer militan, ada pula bayaran.
Kerap, meski hajatan sudah usai namun segregasi sosial tetap ada, berlanjut bahkan permanen dengan bukti istilah/julukan ejekan (Kadrun, Cebong, dan seterusnya) yang dilekat di masing-masing kelompok.
Geopolitik mengendus, ada benih ditebar serta dipelihara agar perputuasi kegaduhan terus berlangsung melalui kiprah para buzzer dan/atau influencer.
Pertanyaannya ialah, “Ini skenario untuk memelihara konflik supaya bangsa ini terus gaduh di tataran hilir, sehingga abai terhadap persoalan hulu bangsanya, atau akibat lemahnya leadership dalam mengendalikan publik?”
Berbasis pengalaman, bahwa keadaan semacam ini menyebabkan pertemanan kadang bubar, saudara pun bisa menjadi lawan dan seterusnya. Dan sungguh aneh, ketika ada selompok orang justru bangga dipuji asing sebagai negara paling demokrasi, sedang rasa persatuan dan kesatuan semakin tercabik di depan mata. Retorika selidiknya adalah, “Ini hajatan mencari pemimpin atau hidden agenda guna memecah belah bangsa?”
Sang pujangga turun gunung, “Bukankah sila ke-4 Pancasila menganjurkan agar pemimpin itu harus dicari melalui mekanisme musyawarah mufakat sebab akan ditemui hikmat/kebijaksanaan di sana?”
Pujangga pun menekankan, “Gunakan local wisdom (kearifan lokal). Itu ajaran leluhur, Nak”.
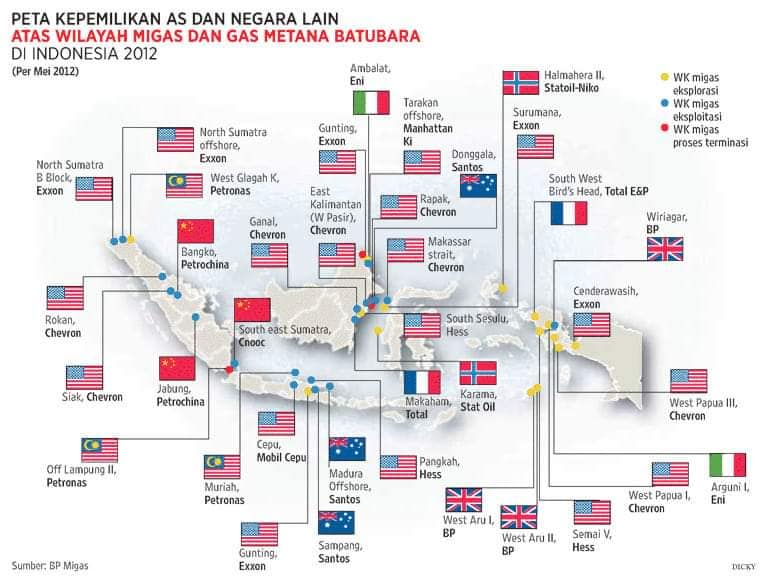
Geopolitik mengajarkan, bahwa kearifan lokal merupakan pasak penghubung (linking pin) antara masa lalu, masa kini dan masa depan. Hikmat yang dapat dipetik, tak usah membeo kepada nilai luar hanya untuk menjadi besar kembali, cukup menarik hikmat masa lalu karena nenek moyang kita tempo doeloe sesungguhnya adalah bangsa yang besar.
Betapa nilai-nilai kejayaan yang susah payah digali oleh para pendiri bangsa (founding fathers), tetapi sekarang diabaikan bahkan dicampakkan justru melalui (sistem) UUD itu sendiri.
Fenomena macam apakah ini?
Ya. Begitu lembutnya skema penjajahan (gaya baru) karena nyaris tidak teraba. Tak terasa. Tanpa letusan peluru, sebagian anak bangsa saling memecah diri dan membelah masyarakat (melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa), lalu dengan bangga menyebut sebagai kelompok ini, golongan itu dan seterusnya. Sebagian bangsa ini nyaris tanpa sadar lagi tidak memahami, bingung siapa gerangan si pemecah belah bangsanya.
Nah, fenomena di atas kerap disebut dengan istilah invisible hands alias tangan-tangan tersembunyi. Dan nyatanya memang ia tersembunyi serta bersembunyi di balik sistem dan konstitusi.
Lagi-lagi, geopolitik menemui hal yang sangat riskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal apakah itu? Bahwa terdapat sebagian anak bangsa —kelompok tertentu— malah “jatuh cinta” kepada penjajah. Mereka justru membela serta memperjuangkan kepentingan si penjajah agar misi kolonialisme kian tertancap di Bumi Pertiwi. Sungguh sangat menyedihkan. Retorikanya begini, “Mereka itu tahu atau tidak tahu; atau jangan-jangan berpura tidak tahu karena turut mencicipi efek kolonialisme sistem?”
Akhirnya, sang pujangga berkata lirih, iki zaman kalabendu. Sing tua ora ngerti tuane, sing enom kurang tata kramane. Maka, “Kelak bila mereka duluan menghadap Illahi Rabb, akan kukirim karangan bunga duka cita dengan ucapan: SEMOGA ARWAHMU DITERIMA SI PEMILIK MODAL”.
End
M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)




